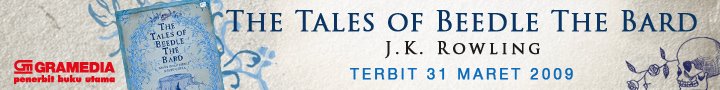“Mahabarata dari sudut pandang Dropadi.”
Waw! Sebagai penggemar Mahabarata saya sudah membaca berbagai versinya. Mulai dari cerita bergambar, sampai kitab lusuh yang berpanjang-panjang memuat percakapan Arjuna dan Kresna saat Arjuna dilanda kebimbangan di medan perang. Tapi belakangan saya agak malas membaca berbagai versi baru Mahabarata yang muncul di toko buku. What's new?
Inilah yang “new”, Mahabarata dari sudut pandang Dropadi. Tokoh kontroversial yang selama ini sangat sedikit diulas, meskipun perannya dalam mencetuskan perang raya di padang Kurusetra lumayan besar. Dan tentu saja versi Mahabarata yang ini sangat baru, karena dipandang dari mata seorang perempuan. Waw! (Sekali lagi.) Divakaruni benar-benar iseng, nekat, sangat imajinatif, dan berani! Dan hasilnya adalah kisah yang benar-benar baru. Penuh rasa, penuh detail, penuh emosi, sangat perempuan. Saya sangat menikmati membaca Mahabarata yang ini.
Diawali dengan latar belakang Dropadi (saya merasa agak aneh dengan penulisan nama ini karena lebih terbiasa dengan “Drupadi”) yang jarang-jarang terungkap, kisah ini awalnya mengalir mulus dan riang. Dropadi cilik sampai remaja adalah gadis cerdas yang selalu ingin tahu dan tidak sabaran. Juga agak tidak pede karena kulitnya hitam. Tapi dia diselimuti cinta kakaknya, Drestadyumna (susah bener, untung sepanjang cerita dia disebut Dre saja) dan sahabatnya Krishna.
Dre dan Dropadi lahir karena ayah mereka, Raja Dropada, ingin balas dendam pada Dorna, brahmana guru para Pandawa dan Korawa. Oleh karena itu Dre dididik komplet soal pemerintahan dan pertarungan, sementra Dropadi nebeng pendidikannya. Tapi sebagai gadis, Dropadi terpaksa tidak bisa mengikuti seluruh langkah Dre, dan harus juga belajar hal-hal kewanitaan.
Suatu saat Dropadi ikut pengasuhnya ke seorang brahmana peramal. Oleh sang brahmana, Byasa (yang menuliskan kisah Mahabarata, dan ikut berperan di dalamnya) Dropadi diberitahu dia akan memiliki 5 suami, dan masa depannya akan heboh banget, terutama karena sifatnya yang tidak sabaran dan pemarah. Dropadi tentu tidak percaya pada ramalan itu. Ia hanya senang karena sang brahmana memberinya nama baru, Panchali.
Selang beberapa lama, Raja Dropada membuat sayembara untuk menikahkan Dropadi. Sasarannya adalah Arjuna, supaya para Pandawa bisa menjadi sekutu mereka saat konfrontasi dengan Drona datang. Saat sayembara, Dropadi menghina Karna (sahabat Duryudana, Raja Angga dan yang disangka anak kusir kereta). Mulailah hubungan cinta dan benci keduanya. Seperti yang diinginkan, Arjuna memenangkan Dropadi dan membawanya kepada saudara-saudaranya. Tak disangka, di pintu rumah, gurauan Bima disambut Kunti (ibu para Pandawa) dengan “Apa pun yang kalian bawa itu harus dibagi untuk kelima putraku.” Dengan demikian jadilah Dropadi istri kelima Pandawa, sesuai ramalan Byasa. Dengan pengaturan tertentu, Dropadi berganti suami setiap satu tahun sekali.
Para Pandawa membawa Dropadi ke Hastinapura, lalu ke daerah yang diberikan Drestarata si raja buta kepada mereka. Di daerah baru itu mereka membangun Istana Khayalan, tempat yang sangat dicintai Dropadi. Wilayah yang asalnya gersang itu pun segera menjadi makmur, dan disebut Indraprastha.
Bencana datang dalam bentuk permainan dadu. Saat memenuhi undangan Duryudana untuk datang ke Hastinapura, Yudistira kalah main dadu dan kehilangan segalanya; kekayaan, istana, adik-adiknya, dan bahkan Dropadi. Dropadi diseret ke ruang singgasana, dan akan ditelanjangi. Dengan bantuan dewata, niat jahat itu gagal. Dropadi bersumpah tidak akan menyisir rambutnya lagi sebelum mengeramasinya dengan darah para Korawa.
Para Pandawa terbuang ke hutan selama 12 tahun. Dropadi menyertai suami-suaminya. Di tahun ke-13, mereka bersembunyi di istana Wirata. Selanjutnya menyusun kekuatan untuk menyerang para Korawa.
Di bagian ini cerita menjadi gelap karena Divakaruni dengan piawai memaparkan dendam dan kebencian perempuan yang dipermalukan. Perempuan yang harus mendorong para lelakinya untuk membela kehormatan dirinya. Perempuan yang berusaha dengan cara apa pun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Perempuan yang mengerikan.
Perang pecah, dan berakhir mengerikan. Meskipun Pandawa menang, tapi mereka kehilangan makna kemenangan itu sendiri. Saat mereka memerintah Hastinapura dan menjadikannya kerajaan yang makmur sekalipun, bayang-bayang dosa-dosa perang tidak bisa meninggalkan mereka.
Secara garis besar, kisah ini sama sekali tidak melenceng dari Mahabarata yang saya kenal. Tapi bumbu-bumbunya membuat kisah ini berbeda. Dan makna yang tersirat pada kisah ini sangat jelas. Belajarlah mengontrol emosi, belajarnya menjadi dewasa, buanglah dendam. Dan tentu saja, tidak ada manusia yang sempurna. Selain itu kisah cinta Dropadi dengan lelaki-lelakinya juga sangat menarik. Utamanya hubungannya dengan Karna dan Krishna. Betapa Dropadi mencintai Krishna secara platonis, selalu kehilangan Krishna, selalu ingin didampingi Raja Dwaraka itu. Sementara dengan Karna, hati Dropadi terbelah. Sedari remaja dia naksir sang Raja Angga, tapi takdir menetapkan mereka selalu berseberangan. Di detik terakhir, Dropadi baru tahu bahwa Karna pun mencintainya, tapi sudah takdir Karna untuk mati di padang Kurusetra.
Anyway, siapa pun yang tertarik pada Mahabarata atau pada seluk-beluk gelap pikiran perempuan harus membaca buku ini. It's a page turner, jelas tidak rugi menguliknya.
Wednesday, July 29, 2009
Palace of Illusions ~ Chitra Banerjee Divakaruni
Posted by Donna at 7:58 AM 0 comments
Labels: Ulasan
Sunday, July 12, 2009
Khatulistiwa-Edward Stefanus Murdani
Di negara kepulauan terbesar di dunia ini, sebetulnya menyedihkan tidak banyak novel yang menjadikan laut, berenang, berlayar, dan main-main air sebagai latar belakangnya. Syukurlah ada Khatulistiwa.
Tema pelayaran erat sekali membungkus semua alur cerita novel ini. Khatulistiwa adalah nama perahu layar mungil yang dimiliki Alex, tokoh utamanya. Yah, meskipun Indonesia negara kepulauan, tapi nggak semua orang di negara ini bisa punya perahu sih. Alex kebetulan beruntung karena kakeknya yang pengusaha perkapalan besar (jenis tanker gitu kali) mewariskan perahu layar ini pada cucu semata wayangnya.
Alex lebih banyak menghabiskan waktunya di atas Khatulistiwa dan berlayar mengelilingi Kepulauan Seribu di utara Jakarta. Pasalnya, dia memang gerah di rumah karena orangtuanya acap bertengkar soal ini-itu. Selain itu, Alex juga “menghindar” dari Siska, cewek yang ditaksirnya, karena mendapat peringatan dari ibu cewek itu bahwa Siska sudah dijodohkan dengan Randy, anak teman bisnis keluarga mereka.
Saat libur kelulusan SMA, Alex berniat berlayar agak jauh ke Kepulauan Karimun Jawa di utara Semarang, dan pulang untuk minta izin orangtuanya. Tak disangka, begitu sampai di rumah, dia menyaksikan orangtuanya sedang bertengkar dan ayahnya menyebut dirinya anak haram. Bukan hanya itu, ayahnya juga memukul ibunya. Alex balik memukul ayahnya, lalu lari kembali ke Khatulistiwa.
Setelah mengetahui ayah kandungnya ternyata tinggal di Kepulauan Natuna, Alex putar haluan ke utara, berniat pergi ke kepulauan dekat Singapura itu untuk mencari ayahnya. Siska ingin ikut, karena ingin menjauh juga dari Randy.
Mulailah kedua remaja itu menyusun rencana. Alex mengajari Siska berbagai hal mengenai pelayaran dan cara menjalankan kapal. Siska menyetok gudang Khatulistiwa dengan berbagai makanan enak untuk bekal selama perjalanan.
Persiapan mereka diganggu Randy yang sempat meracun Skipper—anjing golden retriever kesayangan Alex. Untung Skipper bisa diselamatkan.
Alex dan Siska bekerja keras supaya bisa berangkat secepatnya, tapi suatu malam Siska muncul dengan keadaan kacau balau, mengaku baru akan diperkosa Randy. Keadaan itu memaksa mereka untuk segera berlayar, siap atau tidak.
Perjalanan sampai ke Kepulauan Seribu cukup lancar. Tapi sampai di Pulau Sepa, Randy dan kawanannya menghadang mereka, memukuli Alex, dan membawa Siska. Dengan upaya keras, Alex berhasil membawa kembali Siska. Mereka langsung berangkat menuju Pulau Bangka.
Pulau Bangka berhasil mereka capai, dan baru mereka menghubungi orangtua mereka. Tidak heran, mereka dimarahi habis-habisan. Orangtua Siska bahkan mau melaporkan Alex ke polisi. Tapi di luar masalah itu, kedua remaja ini bersenang-senang menikmati laut Pulau Bangka yang jernih, dan kekayaan kuliner pempek, ikan bakar, dll, yang nikmat.
Perjalanan dilanjutkan ke Kepulauan Natuna. Mereka sempat dihadang perompak, cuaca buruk, juga sempat mengalami masalah di jalur laut yang padat. Tapi, sampai di Natuna, mereka ternyata berhasil menemukan ayah kandung Alex!
Apakah kisah ini berakhir bahagia? Masih ada kejutan seru di ujung cerita.
Si pengarang yang rupanya juga bukan anak laut (data diri menyebutkan dia tinggal di Bogor dan Bandung) pasti bekerja keras sehingga cerita pelayaran, bentuk kapal, kejadian-kejadian di laut, dan rute pelayaran Jakarta – Kepulauan Natuna bisa tampil sangat mendetail dan hidup. Bukan hanya itu, detail-detail kapal layar dan data teknis, deskripsi tentang laut dan kekayaan alam tempat-tempat yang dikunjungi Alex dan Siska juga sangat menggugah dan enak dinikmati. Selain itu deskripsi yang enak dinikmati juga deskripsi tentang makanan. Bekal kornet buatan Siska, spageti, lontong sayur buat sarapan, dan makanan yang mereka santap di Bangka. After all, bukankah kata orang angin laut itu membuat lapar?
Posted by Donna at 8:48 AM 3 comments
Labels: Ulasan
Howl's Moving Castle-Diana Wynne Jones
Ini buku yang aneh. Tapi begitulah kebanyakan buku fantasi, bukan? Satu hal yang saya sukai dari buku ini (selain cover versi Indonesia-nya yang brilian banget!), adalah dia berbeda dengan filmnya. Terus terang, di tengah membaca Howl's Moving Castle, saya menonton animasinya. Animasinya, menurut saya, yah... jelek. Payah. Tidak menggugah. Dan jauh lebih aneh daripada bukunya. Sedih deh pokoknya.
Sementara bukunya, sebetulnya lucu. Lucu banget malah! Dan mengeksplorasi cerita yang sangat bisa dinikmati oleh pembaca anak-anak. Meskipun aneh... hahaha...
Jadi, begini... Cerita ini berlangsung di Ingary, negeri sihir, tempat nenek sihir atau penyihir itu hal yang wajar, dan orang biasa minta jampi-jampi untuk hidup sehari-hari dan takdir ini-itu merupakan hal biasa. Demikian pula takdir, Sophie Hatter, tokoh utama buku ini. Sophie ditakdirkan sial karena lahir sebagai anak pertama dari 3 bersaudara yang cewek semua. Takdir sial itu menjadi nyata saat Nenek Sihir dari Waste yang jahat karena satu dan lain hal yang baru ketauan di ujuuuuuuuuuuuung cerita, benci padanya, dan menyihirnya menjadi nenek-nenek.
Sophie yang aslinya masih remaja itu pergi dari rumah dan terpaksa berlindung di Istana Bergerak milik Penyihir Howl. Sebenarnya penduduk sekitar takut pada penyihir ini karena gosipnya dia suka memangsa gadis-gadis muda. Ndilalah, ternyata Howl cuma penyihir pemalas yang playboy cap duren tiga! Segala tingkah Howl yang bolak-balik naksir cewek dan patah hati inilah yang membuat kelucuan sepanjang cerita.
Sementara itu istana bergerak bisa berjalan terus karena ada Michael, murid Howl, yang bersih-bersih dan mengurus istana, serta Calcifer, si jin api yang tinggal di perapian dan membuat sihir supaya istana bisa berpindah-pindah tempat. Sophie segera bergabung dengan keduanya, dan berusaha keras supaya istana bisa terlihat rapi, bersih, dan mengurus Howl supaya tidak lupa mencari nafkah bagi mereka (dengan menjual mantra). Tentu saja, diam-diam Sophie membuat perjanjian saling membebaskan dengan Calcifer. Sophie akan mencoba mematahkan mantra yang mengikat Calcifer pada Howl, dan sebagai imbalannya Calcifer akan mengembalikan Sophie ke wujudnya yang gadis remaja.
Dalam perjalanan waktu, Sophie mendapati bahwa Howl mungkin naksir adik perempuannya. Oh, gawat! Sophie berusaha menggagalkan niat Howl. Tapi kemudian mendapati Michael ternyata pacaran dengan adik perempuannya yang lain! Sementara itu Howl pergi ke tanah Wales, lewat pintu ajaib, dan sepertinya naksir Miss Angorian. Sophie makin kelabakan. Di lain pihak, Howl mendapat perintah dari Raja untuk mencari adiknya, Pangeran Justin dan penyihir kerajaan, Suliman, yang hilang. Kemungkinan mereka hilang disihir Nenek Sihir dari Waste. Howl yang pemalas berusaha menghindar dari tugas itu dan melibatkan Sophie supaya berpura-pura jadi ibunya di depan raja dan memberikan rekomendasi buruk.
Cerita makin ruwet dan aneh saat ibu tiri Sophie serta adik-adiknya muncul, dan Nenek Sihir dari Waste berhasil melacak dan menyandera keluarga Howl supaya penyihir itu mau bertarung dengannya. Dan akhirnya Sophie memberanikan diri masuk ke markas besar Nenek Sihir dari Waste.
Ujungnya? Biarpun aneh dan ruwet, sebetulnya novel ini lucu dan menghibur dan penuh hal ajaib—bahkan bunga-bunga indah yang mekar dengan sihir. Jelas, berbeda jauh dengan animasinya yang tiba-tiba bercerita tentang perang. Perang? Hah? Di Ingary? Hahaha... Dalam cerita tentang para penyihir yang malas dan nenek-remaja yang sok tahu ini, kayaknya perang membutuhkan komitmen yang terlalu besar.
Posted by Donna at 8:36 AM 3 comments
Labels: Ulasan
Tuesday, May 12, 2009
Shakespeare dalam Manga
 Oleh: Ratih Kumala
Oleh: Ratih KumalaPertama kali saya berkenalan dengan Shakespeare lewat Romeo and Juliette yang saya tonton filmnya di TVRI, ketika saya masih SD. Film itu dilengkapi dengan subtitle Bahasa Indonesia yang sangat membantu saya sebab waktu itu saya tidak bisa berbahasa Inggris. Saya tidak tahu siapa itu William Shakespeare, tapi film Romeo and Juliette ketika itu lumayan membekas di benak saya. Beberapa tahun kemudian, saya baru tahu kalau film itu sejatinya diangkat dari karya seseorang bernama William Shakespeare. Beberapa tahun kemudian (lagi) saya juga baru tahu kalau karya Shakespeare itu bukan novel, novelet atau cerpen, melainkan naskah drama teater. Kesimpulannya: saya lumayan lambat mengenal siapa itu Shakespeare, hehehe….
Ketika kuliah di jurusan Sastra Inggris, agaknya rada memalukan kalau tidak mengenal karya-karya Shakespeare. Terlebih lagi karena dosen-dosen saya kerap menyebut-nyebut namanya. Saya sempat ke perpustakaan kampus dan membaca buku William Shakespeare, dan hasilnya … (sejujurnya) saya bingung! Bahasa yang digunakan masih jadul (atau ‘klasik’, sebutan yang lebih elegan). Bahasa Inggris klasik tidak pernah benar-benar diajarkan di kampus. Untuk memahami sebuah kalimat berbahasa Inggris klasik, saya waktu itu bolak-balik membuka kamus, lumayan melelahkan. Mungkin ini adalah pengakuan dosa paling blak-blakan yang pernah saya lakukan: sewaktu jadi mahasiswa Sastra Inggris, saya lebih suka menonton film yang diangkat dari karya William Shakespeare ketimbang membacanya (semoga Tuhan mengampuni saya). Kisah-kisah yang ditulis Shakespeare bagi saya lebih mudah dipahami dengan menonton televisi. Satu-satunya kalimat yang paling saya ingat dari Shakespeare adalah “What’s in a Name?” (apalah arti sebuah nama?) Ketika Juliette ngomong sendiri di jendela kamarnya, sementara Romeo nguping setelah tresspassing dengan cara lompat pagar. Lain itu, tidak. Alhasil, dari menonton itu: saya mengetahui jalan cerita karya-karya Shakespeare, tapi tidak menghapal kalimat per kalimat -ini hal yang lumayan memalukan sebagai seorang lulusan Sastra Inggris-. Mungkin saya satu-satunya orang yang mengakui hal (memalukan) ini; tapi saya tahu tidak sedikit mahasiswa Sastra Inggris (di Indonesia) yang melakukan hal sama seperti saya. Hanya saja mereka masih punya harga diri untuk tidak mengakuinya hehehehe.
Ketika masih kuliah, saya lebih suka membaca puisi-puisi karya Robert Frost, Emily Dickinson, Oscar Wilde, EE Cummings, dll. Entah kenapa, saya banyak jatuh cinta pada puisi-puisi berbahasa Inggris. Saya juga membaca prosa (novel/cerpen) berbahasa Inggris yang dijadikan bacaan wajib oleh dosen (umumnya karya klasik seperti Gone With The Wind, karya-karya Mark Twain, dll). Karya sastra prosa yang lebih saya nikmati justru lebih banyak berbahasa Indonesia. Waktu itu, saya mirip Sponge Bob, menyerap bacaan sastra Indonesia yang mana pun. Jika ada prosa berbahasa Inggris yang betul-betul saya nikmati maka itu karya moderen seperti serial Harry Potter. Kalau saya merasa sudah terlalu bosan melihat huruf, saya beralih ke komik. Saya punya langganan taman bacaan dekat rumah, di mana saya biasa menyewa komik, kebetulan di sana lebih banyak menyediakan manga (selain Ko Ping Ho). Untuk yang satu ini, saya tidak pemilih. Saya melahap hampir segala jenis manga, baik untuk anak lelaki (seperti Kungfu Boy, Conan, Dragon Ball) maupun untuk anak perempuan (seperti Candy-Candy, Pop Corn, dan manga Serial Cantik).
Kesenangan saya akan komik sampai sekarang masih terjaga. Saya masih membaca ulang Asterix, ikut girang ketika Tin Tin diterbitkan ulang (meskipun kalimat “sejuta topan badai” diganti, hiks…), juga mengikuti beberapa manga terbaru seperti Miko, Vegabound dan Showa Man. Lebih dari itu, saya girang betul ketika dihadiahi seorang teman tiga buku membuat komik karya Scott McCloud: Understanding Comics, Reinventing Comics dan Making Comics. Akhir-akhir ini, saya juga sangat menikmati membaca novel grafis seperti karya-karya Frank Miller dan Marjane Satrapi. Entah kenapa, segala hal yang lebih visual (ada gambarnya) bagi saya sangat menghibur.
Ketika saya tahu karya-karya William Shakespeare disajikan dalam bentuk manga, reaksi saya pertama adalah: “hah?!” dengan heran. Apalagi ketika saya baca balon di manga (Bahasa Inggris) ini ternyata berbahasai Inggris klasik alias aseli tulisan Shakespeare (yang dulu sempat bikin saya bingung). Saya bertanya-tanya sendiri: apakah pembaca (Bahasa Inggris) akan memahaminya? Lalu, tiba-tiba saya tersadar: hey, ini Shakespeare dalam bentuk manga, jadi sesulit apapun karyanya, visual manga akan sangat membantu pembaca: inilah keuntungannya. Seperti menonton filmnya, hanya saja dalam film, penonton tidak bisa memperhatikan kalimat per kalimat dialog, terutama jika itu adalah Bahasa Inggris klasik, dan jika pun ada subtitle Bahasa Indonesia, penonton hanya diberikan waktu tiga hingga lima detik untuk membaca tiga baris subtittle. Lain halnya dengan membaca Shakespeare manga karya Adam Sexton dan Yali Lin ini.
Saat ini ada empat judul Shakespeare versi manga yang telah terbit dalam Bahasa Indonesia: Hamlet, Macbeth, Romeo & Juliet, dan Julius Caesar. Meskipun membaca Shakespeare dalam Bahasa Indonesia (bagaimanapun) berbeda “rasa” dengan membaca bahasa aseli, tapi Shakespeare versi manga bisa menjadi pintu perkenalan kita sebelum benar-benar membaca karya Shakespeare dengan bahasa Inggris klasik. Minimal, memperkenalkan jalan cerita mahakarya ini secara lebih intens kalimat per kalimat.
Sebuah karya sastra begitu dipuja, sehingga orang mencari cara agar bisa dinikmati semua kalangan dan semua umur. Itulah karya William Shakespeare.
Tentang Ratih Kumala:
Ratih Kumala lahir di Jakarta, 4 Juni 1980. Ia lahir dan besar di keluarga Betawi-Jawa. Penulis yang menikahi Eka Kurniawan ini telah menerbitkan 3 buku. Novel terbarunya, Kronik Betawi, segera terbit pada bulan Juni 2009.
Posted by editor at 11:05 AM 0 comments
Labels: Ulasan
Tuesday, May 5, 2009
Brisingr~Christopher Paolini
“Buku yang membuat saya rela bergadang.”---Washington Post.
Dan tepat itulah yang saya lakukan satu setengah minggu ini. Brisingr edisi Indonesia yang tebalnya kurang-lebih 900 halaman itu membuat saya tidur tengah malam selama berhari-hari karena adegan-adegannya yang seru.
Saat membaca Eragon, saya merasa wagu karena banyak kemiripannya dengan The Lord of the Rings---mungkin juga karena masa itu trilogi LOTR juga lagi naik daun. Selain itu, tulisan Paolini pun masih terasa sangat kekanakan. Saat Eldest, dialog-dialog panjang pelajaran Eragon terasa membosankan, dan petualangan Roran terasa lebih seru. Tapi pada Brisingr, semua elemen cerita terasa seru dan perlu. Brisingr menyuguhkan petualangan demi petualangan, perang demi perang, perkelahian demi perkelahian baik secara fisik langsung maupun dengan sihir. Semuanya seru dan intens, dan meskipun ukuran bukunya yang hampir 900 halaman tampak masif, secara keseluruhan buku ini sama sekali tidak membosankan.
Paolini jelas telah berkembang dengan baik sebagai penulis (dan kalau dilihat dari fotonya, sebagai pemuda juga... hehehe). Ia bisa menautkan simpul-simpul lepas dan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tak terjawab yang ada pada buku-buku sebelumnya. Ia bisa memberi kilas balik dan penjelasan dengan sangat baik dengan menyelipkannya pada dialog-dialog, sehingga pembaca mengerti dan tidak merasa digurui. Ia bisa memberi gambaran sejelas film action pada adegan-adegan laganya. Dan utamanya, ia berhasil menciptakan dunia Alagaësia yang utuh, baik itu dunia sihirnya maupun dunia manusianya. Saat membaca Brisingr, saya tidak lagi berusaha membanding-bandingkan Kull dengan Uruk Hai atau elf di Alagaësia dengan elf di Middle Earth.
Cerita dibuka dengan seru saat Eragon membantu Roran merebut kembali Katrina dari tangan para Ra'zac. Tekanan kengerian ditambah Paolini dengan meninggalkan Eragon di Helgrind, sarang Ra'zac tanpa Saphira yang harus membawa pulang Roran dan Katrina ke markas Varden. Pertempuran Eragon dan Ra'zac yang seru diikuti kisah Eragon (dan Arya) menjelajah Kekaisaran untuk kembali ke Varden serta apa yang dialaminya saat itu sangat patut disimak.
Sementara itu di markas kaum Varden, Nasuada harus mempertahankan wibawa dan kepemimpinannya dengan Duel Pisau Panjang yang mengerikan. Dan Roran memutuskan untuk mengabdikan diri padanya (kedua hal ini sebetulnya tidak berkaitan secara langsung). Roran lalu terlibat dalam berbagai pertempuran “kecil” dan membuktikan dirinya pantas menjadi pejuang dan pemimpin.
Saat kembali ke Varden, Eragon (dan Saphira) harus menghadapi Murtagh dan Thorn sekali lagi. Dalam pertempuran kali ini Eragon dan Saphira yang dibantu dua belas elf perapal mantra dan Arya berhasil mengusir dan mengalahkan Murtagh dan Thorn. Tapi pertempuran “di tanah” mengalami kekacauan besar, saat pasukan Varden mendapati Galbatorix telah menciptakan prajurit-prajurit perang yang tak bisa mati kecuali dipenggal. Meskipun berhasil menghancurkan pasukan Galbatorix, kaum Varden mengalami kerugian besar.
Usai menikahkan Roran dan Katrina, Eragon ditugasi oleh Nasuada untuk pergi kepada kaum kurcaci di Pegunungan Beor untuk memastikan raja kurcaci yang baru mendukung perjuangan kaum Varden. Sekali lagi Eragon dan Saphira harus berpisah. Eragon pergi ditemani Nar Garhzvog, pemimpin Kull. Sampai di tempat saudara angkatnya, Grimzborith Orik yang mengepalagi klan Ingeitum, Eragon mendapati bahwa ia mungkin harus mengikuti rapat kaum kurcaci yang bisa berlangsung berminggu-minggu dan tidak bisa melakukan apa-apa untuk mempercepat prosesnya.
Saat tiba di kota bawah tanah kaum kurcaci, ternyata secara tidak langsung Eragon dapat mempercepat proses pemilihan raja itu karena percobaan pembunuhan yang dilancarkan padanya oleh salah satu pemimpin klan. Orik terpilih menjadi raja baru, dan dukungannya pada kaum Varden bisa dipastikan. Eragon dan Saphira menghadiri upacara penobatannya, lalu terbang ke kota kaum elf, Ellesmera, di tengah hutan Du Weldenvarden.
Di sana, saat bertemu dengan gurunya, Oromis dan naganya Glaedr, Eragon mendapati bahwa ternyata dirinya bukan putra Morzan dan adik Murtagh. Dengan lega, Eragon mengetahui bahwa ayahnya ternyata Brom, yang ia anggap gurunya yang pertama. Berikutnya, Eragon---yang sepanjang berbagai pertempuran merasa tidak memiliki senjata yang tepat sejak Za'roc diambil Murtagh dari tangannya---berusaha membujuk elf tua Rhunon untuk membuatkan pedang baginya. Rhunon sudah bersumpah tidak akan membuat pedang lagi sejak senjata buatannya dipakai untuk membantai naga dan penunggangnya oleh Galbatorix. Tapi, kalaupun ia mau melanggar sumpahnya, ia tidak memiliki bahan untuk membuat pedang lagi karena bahan tersebut besi yang terkandung dalam komet yang jatuh di Du Weldenvarden.
Mengikuti saran Solembum, si kucing jadi-jadian, Eragon dan Saphira mencari besi tersebut di bawah akar pohon Menoa yang tertua di Du Weldenvarden. Mereka membangkitkan kemarahan pohon tersebut, tapi berhasil meyakinkannya untuk menyerahkan besi itu. Semalaman Eragon menjadi “alat” Rhunon, yang untuk menjaga sumpahnya tidak menempa sendiri besi tersebut, untuk membuat pedangnya sendiri. Paginya, pedang biru seperti sisik Saphira telah jadi. Pedang terindah yang “dibuat” Rhunon. Eragon menamai pedang itu Brisingr, alias api dalam bahasa kuno. Setiap kali ia mengucapkan nama pedang tersebut, pedang itu menyalakan api biru.
Kunjungan Eragon dan Saphira pada guru-guru mereka juga memberikan pengetahuan baru tentang Eldunari naga, jantung dari jantung naga, tempat mereka menyimpan seluruh kesadaran dan pengetahuan mereka. Mereka juga mengetahui bahwa kekuatan Galbatorix datang dari kumpulan Eldunari yang ditawannya. Pada akhirnya, sebelum Oromis dan Glaedr ikut terbang untuk berperang bersama Ratu Islanzadi, Glaedr memberikan Eldunari-nya untuk dijaga Eragon dan Saphira.
Kembali ke kaum Varden, Eragon dan Saphira segera terlibat dalam perang menjatuhkan kota Feinster. Reuni dengan Arya, Roran, dan yang lain yang awalnya gembira harus diakhiri dengan sedih saat lewat Eldunari Glaedr, mereka mendapat kejutan besar.
Demikian buku ketiga ini ditutup dengan baik oleh Paolini, meninggalkan banyak pertanyaan untuk dijawab pada buku keempat. Antara lain pertanyaan yang berkaitan dengan ramalan mengenai nasib Eragon yang beberapa kali dikutuk untuk meninggalkan Alagaësia. Apakah setelah menaklukkan Galbatorix, satu-satunya penunggang naga yang merdeka itu harus meninggalkan tanahnya? Atau jangan-jangan Galbatorix memang tak terkalahkan? Rasanya pertanyaan terakhir ini---meskipun apa pun mungkin saja terjadi di dunia fiksi---tidak mungkin terjadi. Semua kisah epik kebaikan vs. kejahatan pasti berakhir dengan kekalahan pihak yang jahat. Tapi bagaimana si jahat mati? Semua pasti menunggu-nunggu pertempuran akhir antara Eragon dan Saphira vs. Galbatorix dan Shruikan. Sssshhh... penantian yang panjang pun dimulai...
Posted by Donna at 2:58 AM 1 comments
Labels: Ulasan
Eiffel, Tolong!~Clio Freya
Ada beberapa buku yang membuat saya bangga terlibat dalam kelahirannya. Novel ini salah satunya. Bangganya saya itu berkaitan dengan betapa rapinya novel ini. Sebenarnya, selain untuk meluruskan beberapa titik-koma, novel ini tidak perlu editor.
Kenapa rekomendasi saya bisa begitu berbunga-bunga? Saya tidak biasa memuji, bahkan agak muak dengan novel-novel yang dipuja-puji orang. Euh, apa novel-novel itu tidak bisa "Speak for themselves"? Jadi, moga-moga puji-pujian saya ini tidak membuat yang membaca resensi ini malah jadi muak pada "Eiffel, Tolong!"
Bisa dibilang menjual kata "Eiffel", yang jadi magnet buat pembaca di mana-mana di seluruh dunia, novel ini memulai dirinya dengan judul yang tepat. Judul juga bisa mengantar pembaca kecele menduga ini novel cinta macam "Eiffel, I'm in Love". Tapi, tidak!
Bersiapkan terseret dalam dunia thriller yang seru, penuh adegan laga, dan spionase macam serial Alias, CSI, atau Mission Impossible. (Salah satu pertanyaan saya waktu bertemu pengarangnya adalah, "Kamu suka nonton Alias, ya?"--soalnya saya suka sekali serial itu.) Tokoh-tokohnya yang masih remaja--dan mengakibatkan buku ini terpaksa masuk genre teenlit--tidak mengurangi keseruan cerita. Tapi jangan bayangkan juga ceritanya jadi kayak teen spy atau seri Alex Rider-nya Horrowitz.
Anyway, adalah Fay, remaja Jakarta kelas 2 SMA yang berlibur ke Paris sendirian. Tadinya dia ke Paris karena ikut ibunya yang tugas ke sana, tapi detik terakhir tugas ibunya dipindah ke Brazil. Rencananya Fay akan ikut sekolah bahasa Prancis selama 2 minggu, lalu ikut tur selama 3 hari.
Semangat, semangat, semangat! Bagi orang yang pernah menghabiskan 3 hari di Paris, saya langsung membayangkan kegiatan Fay. Apa dia ke Eiffel, Louvre, dkk?
Salah besar, sodara-sodara! Fay ternyata terjebak dalam konspirasi bisnis dan militer mengerikan yang dijalankan oleh Andrew, konglomerat yang mau menghalalkan segala cara demi berhasilnya bisnis yang dijalankannya.
Dianggap mirip sekali dengan keponakan saingan bisnisnya yang orang Malaysia, Andrew menculik Fay dan men-trainingnya sehingga menjadi fotokopi sang keponakan. Dua minggu yang seharusnya jadi 2 minggu terindah dalam hidup Fay berubah bersimbah air mata.
Fay yang gak hobi olahraga dipaksa lari lintas alam dan push-up setiap hari. Fay yang gak pernah dandan dipaksa belajar memoles wajah dan memakai sepatu hak tinggi. Dan Andrew tidak segan-segan menerapkan hukuman fisik bila Fay menolak.
Tapi bukannya tidak ada sparks yang menyenangkan. Fay berjumpa Reno dan Ken. Ken, keponakan Andrew, menjadi mentornya. Sementara Reno adalah teman les bahasanya. Meski awal hubungannya dengan Ken suram, pemuda ini malah membuatnya merasakan sekilas summer love. Sementara Reno selalu melindunginya bak kakak.
Saat Fay sudah sempurna berubah menjadi Sheena, si gadis Malaysia, ia diterjunkan masuk ke rumah saingan bisnis Andrew. Tapi tugas yang mustahil itu akhirnya...
Wah, seru bin asyik banget membaca novel yang sangat rapi ini. Serasa nonton film! Dan... baiklah saya hentikan resensi ini sebelum lebih memuji lagi.
Posted by Donna at 2:55 AM 5 comments
Nicholas Evans
Saya baru menginjak bab kelima The Divide, saat terpesona sungguh pada kepiawaian Nicholas Evans melukiskan emosi tokoh-tokohnya. Saya benar-benar bisa merasa ikut berada dalam setting cerita, dan terlibat dalam kejemuan yang dialami sang tokoh, Sarah Cooper.
Setting-nya sebagai berikut: pagi hari, Sarah ikut sarapan bersama Ben, mantan suaminya dan sheriff lokal. Mereka berada di Missoula, Montana, akan menjemput jenazah putri Sarah dan Ben. Evans menggambarkan kejadian itu dengan sangat detail, berapa pil penghilang rasa sakit yang ditelan Sarah, apa yang dialaminya sejak malam sebelumnya, sampai ke roti gandum yang dipesannya tapi tak mampu ditelannya. Saya langsung bisa berempati pada tokoh ini, dia datang untuk menjemput putrinya yang sudah meninggal, tapi terpaksa melayani basa-basi dengan mantan suami dan sheriff lokal itu. Sungguh dahsyat.
Tapi kemudian Evans mulai menarik-ulur rasa empati dan simpati pembaca pada tokoh-tokohnya. Bagaimana sebenarnya Sarah yang sepertinya patut dikasihani, ternyata sangat dingin dan tinggi hati. Bagaimana Ben yang sepertinya hangat dan menjadi korban, ternyata juga brengsek. Jadi mana yang benar? Evans sangat piawai menciptakan tokoh-tokoh yang abu-abu, dan justru malah jadi sangat duniawi dan wajar. Semua orang di dunia ini toh abu-abu, mejikuhibiniu, bukan? Orang-orang yang wajar bukanlah tokoh sinetron yang benar-benar hitam-putih, yang jahat benar-benar jahat, yang baik benar-benar baik. Weks, itu cuma terjadi di sinetron! Benar-benar dibuat-buat.
Ternyata ada yang menyebut Evans “the animal writer”. Apa pasal? Dalam dua dari empat novelnya, Evans mengambil tema binatang: The Horse Whisperer dan The Loop. Sementara dari judulnya saja The Horse Whisperer sudah tampak berkutat di dunia kuda, The Loop mengulik masalah serigala yang akan punah. Tapi apa benar Evans cuma menulis tentang binatang? “Kalaupun ada binatang yang saya bahas, itu the human animal,” kata Evans kecewa dalam situsnya www.nicholasevans.com. Sesungguhnya Evans justru sangat tertarik pada manusia, hubungan-hubungan antara para anggota keluarga, suami-istri, ayah-ibu-anak, kakak-adik, dan antarsahabat. Semua novelnya mengisahkan ikatan emosi yang sangat kuat antarmanusia. Ia juga sangat kuat menggambarkan emosi-emosi dan perdebatan yang muncul dalam diri manusia saat terjadi konflik benar-salah.
Ambil contoh novel ketiganya, The Smoke Jumper. Dalam novel ini Evans mengisahkan pergulatan kisah cinta segitiga yang tidak biasa. Bagaimana dua sahabat Ed dan Connor berebut cinta seorang gadis. Mana yang benar dan mana yang salah saat Connor jatuh cinta pada pacar sahabatnya? Bagaimana perasaan-perasaan itu memengaruhi tugas mereka sebagai smoke jumper alias pemadam kebakaran hutan? Bagaimana perasaan ketiga tokoh ini saat Ed kemudian menjadi buta? Evans dengan cerdik menempatkan tokoh-tokohnya sebagai tokoh sehari-hari---the guys next door---yang mungkin saja menjadi Anda atau saya. Semua memiliki sisi baik, semua sulit untuk dibenci, sehingga pembaca benar-benar bisa merasa ikut menjadi tokoh-tokoh tersebut dan terseret dalam pusaran emosi mereka.
Omong-omong soal sisi baik dalam tiap tokoh, rupanya kebiasaan Evans menciptakan tokoh demikian sudah dimulai sejak novel pertamanya, The Horse Whisperer. Bagaimana si ibu bisa saling jatuh cinta dengan si penjinak kuda, saat sebenarnya pernikahannya baik-baik saja dan suaminya sempurna? Pembaca ikut menangis karena tahu si ibu tak bisa meninggalkan suaminya demi si penjinak kuda, karena ya dia tidak bisa melakukan itu. Sisi emosional itulah yang membuat novel ini sangat kuat.
The Divide mengupas lebih dalam hubungan antar-anggota keluarga. Bagaimana kisahnya Ben dan Sarah dan anak-anak mereka. Bagaimana si sulung Abigail yang sempurna bisa berubah menjadi eco-terrorist, bahkan kemudian ditemukan sudah membeku dalam es di pegunungan Montana. Dalam novel keempat ini Evans lebih luwes dalam memberikan alasan-alasan bagi perpecahan keluarga Ben dan Sarah, tapi sayangnya jadi sedikit mengurangi tarik-ulur emosional yang dirasakan pembaca dalam The Horse Whisperer dan The Smoke Jumper.
Yang tidak berkurang adalah perencanaan dalam pengaturan plot. Saat membaca The Divide, saya menyadari betapa jagoannya Evans merangkai plot dan cerita serta menerakan emosi. Semua cerita terasa pas, tidak berlebihan atau berpanjang-panjang (salah satu yang sempat saya rasakan saat membaca The Smoke Jumper, sehingga novel ini meskipun sangat indah bagi saya agak antiklimaks). Saya sempat membalik-balik lagi beberapa adegan yang saya baca di The Divide. Wow, pasti Evans berpikir panjang sebelum menempatkan adegan ini, atau mengarang adegan itu. Semua ada pada tempatnya dengan porsi yang tepat. Inilah penulis yang membuat perencanaan dulu sebelum menulis, penulis yang menggodok dulu sampai matang, sehingga hasil tulisannya tidak bisa tidak menjadi hiburan yang berbobot bagi pembacanya.
Dan pujian terakhir bagi Evans adalah kepeduliannya pada lingkungan. Meskipun lahir dan besar di Inggris, Evans sangat tertarik pada wilayah Midwestern Amerika, tepatnya Montana. Ia menggambarkan daerah yang masih berhutan lebat itu dengan sangat indah. Kegiatan-kegiatan alamnya pun dia ceritakan dengan fasih. Pembaca diajak ikut naik gunung, kayaking, rafting, dan berkuda. Semua kegiatan alam bebas yang menantang dan seru itu membangkitkan sisi petualangan dalam diri pembaca. Dalam The Divide, Evans lebih menekankan lagi pentingnya pelestarian lingkungan dengan menyinggung langsung soal illegal logging dan konferensi-konferensi lingkungan hidup. Kalau salah satu penulis besar---Michael Crichton---menyinggung soal pemanasan global dalam rangka cerita yang jauh lebih bombastis dan multinasional dalam State of Fear, Evans menyampaikan pesan lingkungan hidupnya dengan mengajak pembaca turun langsung ke lapangan, menginjak tanah subur Montana dan mengisi paru-paru dengan aroma hutan yang menyegarkan.
Thursday, December 4, 2008
Kalender Raksasa Dengan 365 Jendela

Buku kalender dengan 365 jendela. Setiap hari, satu jendela. Bukan hanya untuk dibaca, buku ini juga bisa digantung di kamar sehingga setiap pagi kamu bisa membuka jendela baru.
Setiap hari ada kejutan baru: gambar dan syair lucu dari Januari sampai Desember. Setiap bulan memiliki tema yang berbeda supaya kita dapat mengungkap rahasia musim-musim sepanjang tahun bersama tokoh-tokoh lucu ciptaan Tony Wolf.
Intip isinya:


(Disebarkan oleh Dini. Desember 2008)
Posted by editor at 8:03 PM 2 comments
Labels: Ulasan
Wednesday, November 26, 2008
Buku Unggulan Desember 2008

Hening (Silence) – Shusaku Endo
Novel ini mengambil setting di Jepang pada abad ke 17, pada periode Edo. Yesuit Portugis, Sebastian Rodrigues, dikirim ke Jepang untuk mencari tahu keadaan mantan gurunya, Ferreira, yang konon dikabarkan telah murtad karena tidak tahan menanggung siksaan. Pada masa itu di Jepang penganut dan penyebar agama Kristen diburu, dipaksa murtad, dan dibunuh oleh penguasa.
Sesampainya di Jepang, Rodrigues harus bertahan hidup dalam kondisi yang serba minim. Dia kekurangan makanan dan nyaris tak punya tempat tinggal, itu pun masih ditambah dengan orang-orang yang tidak segan mengkhianatinya demi memperoleh imbalan. Kemudian Rodrigues pun tertangkap dan harus menjalani siksaan. Hingga Rodrigues bertanya jikalau Tuhan yang selama ini dianggapnya sumber kasih kenapa Dia bungkam dan hening, tidak berbuat apa-apa.
Pada akhirnya, pertanyaan yang utama adalah: Sanggupkah manusia mempertahankan keyakinannya di tengah masa-masa penuh penganiayaan? Dan benarkah Tuhan hanya diam berpangku tangan melihat penderitaan?
Kutipan Favorit:
Dosa bukanlah apa yang biasanya dikira orang, pikirnya; dosa bukanlah karena mencuri dan berbohong. Dosa adalah kalau orang menginjak-injak kehidupan orang lain secara brutal dan sama sekali tidak peduli akan luka-luka yang ditimbulkannya. (hal. 145)
Kristus Tuhan: Jalan Menuju Kana - Anne Rice
O Tuhan, Allah yang Esa, Allah Tritunggal, apa pun yang telah kukatakan di dalam buku-buku ini berasal dari-Mu, kiranya orang-orang kepunyaan-Mu mengakuinya. Apa pun yang berasal dariku, biarlah Engkau dan orang-orang kepunyaan-Mu sudi mengampuninya.
St. Agustinus.
Anne Rice sudah menulis kisah tentang vampir bahkan ketika Stephenie Meyer masih duduk di TK. The Vampire Chronicles-nya yang legendaris telah membubungkan nama Anne Rice menjadi novelis dalam konsep vampir yang radikal. Hingga saat ini buku-bukunya terjual lebih dari 100 juta eksemplar di seluruh dunia.
Pada tahun 2004, Anne Rice kembali ke iman Katolik-nya yang sudah lama dia tinggalkan. Kini dalam usia 67 tahun, Anne Rice menerbitkan novel kedua Christ the Lord: Jalan Menuju Kana.
Dalam buku pertama: Christ the Lord: Out of Egypt (Kristus Tuhan: Meninggalkan Mesir), Anne Rice mengisahkan masa kanak-kanak Yesus serta perjalanan meninggalkan Mesir bersama kaum keluarganya.
Dalam buku kedua ini: Kristus Tuhan: Jalan Menuju Kana, dikisahkan tentang Yesus yang telah dewasa, pada suatu musim dingin tak berhujan, berdebu, dan banyak desas-desus tentang kegelisahan yang mulai menggeliat di Yudea. Legenda tentang kelahirannya yang ajaib telah banyak dibicarakan orang, tetapi selama ini dia hidup sebagai manusia biasa di antara manusia. Mereka yang mengenalnya dan menyayanginya menunggu-nunggu pertanda tentang takdir yang akan dijalaninya kelak.
Dikisahkan pula bagaimana dia mendapatkan pembaptisan dari Yohanes, konfrontasinya dengan Iblis, dan mukjizat mengubah air menjadi anggur dalam pesta perkawinan di Kana. Dan sebagaimana buku terdahulu, Jalan Menuju Kana juga didasarkan pada Injil serta Perjanjian Baru. Kekuatan buku ini bersumber dari semangat yang dibawa sang pengarang dalam penulisannya dan bagaimana ia memunculkan suara, keberadaan, dan kata-kata Yesus yang menceritakan kisahnya.
Dua penulis ini. Shusaku Endo dan Anne Rice, adalah penulis-penulis yang pulang ke iman awal mereka. Anne Rice dibaptis sejak lahir dalam keluarga Irlandia Katolik yang taat. Shusaku Endo dibaptis menjadi Katolik semasa kanak-kanak. Ibaratnya, mereka memiliki agama yang siap pakai. Namun seiring bertambahnya usia, mereka mulai mempertanyakan iman mereka
Pada masa kuliah Anne Rice meninggalkan agamanya, dan menjadi atheis. Baru pada tahun 2004, Anne Rice bertobat dan kembali memeluk agama Katolik. Berkali-kali Shusaku Endo merasa ingin menyingkirkan ke-Katolik-annya, tapi pada akhirnya dia tidak sanggup.
Melalui medium novel, Shusaku Endo dan Anne Rice menuliskan kisah spektakuler tentang cinta mereka pada Tuhan dan agama yang setelah melewati pencarian dan perjalanan panjang akhirnya membawa mereka sampai ke rumah. Perjalanan pulang yang mendamaikan diri serta kembali ke ke-Katolik-an mereka.
Twilight - Stephenie Meyer
Aduh, novel ini sih udah nggak usah diceritain lagi kali yaaa?
Tapi senang aja melihat edisi khusus novel yang dicetak terbatas ini, secara ada foto-fotonya yang diambil dari film. Edward oh Edward deh pokoknya... Dan aku suka banget cover filmnya... pas banget buat jadi sampul novel. When you can live forever, what do you live for?< (Disebarkan oleh Hetih. November 2008)
Posted by editor at 10:13 PM 0 comments
Sunday, November 23, 2008
Porcupine: Jadi Kakak Pemberani
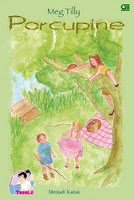 Dari dulu, gue suka banget nonton film bertema perang. Mulai dari seri Band of Brothers yang keren banget, Windtalkers, Tour of Duty (masih ada yang ingat serial ini nggak, ya?), dan banyak judul lainnya. Kenapa? Karena, buat gue, film-film ini menunjukkan sifat aslinya seseorang. Ketika keadaan sudah begitu mendesak, ketika masa depan betul-betul tidak bisa diprediksi, tentara-tentara itu nggak bisa lagi menutupi karakter asli mereka. Kadang, keadaan terdesak justru bisa brings out the best in people. Dan yang juga nggak kalah penting, film-film itu membuat kita belajar untuk jangan lagi berperang, karena ada terlalu banyak yang harus dikorbankan.
Dari dulu, gue suka banget nonton film bertema perang. Mulai dari seri Band of Brothers yang keren banget, Windtalkers, Tour of Duty (masih ada yang ingat serial ini nggak, ya?), dan banyak judul lainnya. Kenapa? Karena, buat gue, film-film ini menunjukkan sifat aslinya seseorang. Ketika keadaan sudah begitu mendesak, ketika masa depan betul-betul tidak bisa diprediksi, tentara-tentara itu nggak bisa lagi menutupi karakter asli mereka. Kadang, keadaan terdesak justru bisa brings out the best in people. Dan yang juga nggak kalah penting, film-film itu membuat kita belajar untuk jangan lagi berperang, karena ada terlalu banyak yang harus dikorbankan.Misalnya keluarga, orang-orang yang harus menderita ketika orang yang mereka sayang nggak bisa pulang lagi. Itu baru buat tentara-tentara yang harus dikirim untuk berperang. Belum lagi penduduk di daerah perangnya.
Nah, kali ini gue bukan nonton film perang, tapi baca buku yang menceritakan kisah yang sering kali cuma dijadikan latar belakang, padahal ini penting banget. Apa yang terjadi pada sebuah keluarga ketika kepala keluarganya harus pergi atas nama tugas.
Sebetulnya ini buku anak-anak, atau lebih tepatnya buku remaja, karena buku ini dikategorikan sebagai teenlit. Meski begitu, Menjadi Kakak (judul aslinya Porcupine) bukan jenis buku yang bisa dibaca sekilas, cepat-cepat, terburu-buru---setidaknya buat gue. Tokoh utamanya Jack Cooper, anak cewek umur 12 tahun pada awal cerita dan berulang tahun ke-13 pada bagian-bagian akhir buku.
Awalnya diceritakan kejadian-kejadian normal di rumah keluarga Cooper. Dengan Jack, yang nama aslinya Jacqueline, yang tomboi dan punya dua adik, Tessa dan Simon. Jack ini tipikalnya daddy’s girl yang jago berantem, nggak ribet, mahir pake alat-alat pertukangan, pokoknya tipe-tipe anak cewek tough deh. Kebalikan banget sama Tessa yang girlie banget dan jadi mommy’s girl, lengkap dengan sepatu-sepatu bagus dan kepangan cantik. Sedangkan Simon anak cowok bungsu yang jago banget main Lego.
Nggak berapa lama, Mr. Cooper harus bertugas ke Afghanistan, dia bukan pergi untuk berperang, tapi jadi tentara penjaga perdamaian PBB. Tapi waktu Mr. Cooper pamitan, ada satu hal yang nggak biasa. Diam-diam, ayah Jack menitipkan arlojinya pada Jack sambil berbisik, “Keep it safe for me.” Mr. Cooper juga sempat meminta Jack untuk menjaga ibu dan adik-adiknya.
Meskipun pergi “cuma”sebagai tentara penjaga perdamaian, hasil akhirnya sama: Mr. Cooper meninggal, gara-gara friendly fire. Dan kehidupan keluarga Cooper langsung berubah drastis. Mrs. Cooper ternyata nggak kuat menghadapi perubahan ini dan menutup diri.
Sampai akhirnya anak-anak harus tinggal dengan nenek buyut mereka (Gran) di kota lain. Padahal Gran sama sekali nggak menyetujui pernikahan ibu dan ayah mereka dulu. Bisa dibayangkan gimana jadinya, kan? Jack harus berusaha keras menyesuaikan diri dengan segala macam perubahan di sekelilingnya, sekaligus membantu adik-adiknya memahami semua perubahan itu.
Jack yang sering kesal sama Tessa akhirnya “berdamai” ketika Tessa berusaha kabur dari rumah Gran. Sekesal-kesalnya Jack, dia tahu mereka bertiga nggak boleh terpisah. Sampai akhirnya, sejak malam itu Jack mulai menambahkan Tessa dalam doa-doanya: And ever since Tessa ran away, I’ve started adding her in my prayers, too. I never did before, because I didn’t know she needed it, but I do now, and I think it helps. Dengan kata-kata sesederhana itu, Meg Tilly---sang penulis---berhasil nunjukin gimana Jack maju selangkah lagi.
Yang pasti, kita nggak perlu balik jadi anak kecil buat bisa merasakan apa yang dirasakan Jack---dan belajar banyak dari Jack. Gimana Jack begitu bahagia ketika suatu malam mimpi ketemu ayahnya, betapa marahnya Jack ketika kaca arloji ayahnya retak waktu dia ngebela Simon yang dikeroyok, gimana kesalnya Jack pada Tessa karena adiknya itu kadang suka egois, atau gimana Jack berusaha banget untuk jadi anak yang tangguh dan nggak pernah mengeluh. Gimana Jack berusaha berani menghadapi hidup.
Menjadi Kakak sebetulnya buku buat semua orang, segala usia. Buku ini ngingetin gue tentang banyak hal, terutama tentang keluarga, what it really means to be a family. Waktu ada beberapa tetangga yang manas-manasin Gran untuk menjual tanahnya dan nggak ngurus cucu-cucunya lagi, melaporkan bahwa Jack nonjok anak cowok di sekolah sampai hidung anak itu retak (waktu Jack membela Simon) dan nyebut Jack sebagai “hooligan”, Gran cuma ngomong gini: “They’re good kids. And I won’t have anybody saying otherwise. Is that clear?” Sederhana banget, kan? Tapi kata-kata sederhana ini punya arti sangat besar buat Jack yang saat itu lagi nguping di ujung tangga. Hihihi… jadi inget kelakuan gue dulu, nguping, mondar-mandir nggak jelas pas ada tamu… siapa tahu lagi ngomongin gue.
Buku ini nunjukin lagi bahwa di balik cerita-cerita perang yang gue suka itu ada cerita lain. Bahwa behind a good story lies great stories. Tapi yang paling penting, lewat buku ini gue jadi tahu bahwa even a porcupine could be petted! You just have to know how….
(Disebarkan oleh Nina. Oktober 2008)
Posted by editor at 5:50 PM 0 comments
Friday, November 21, 2008
Petualangan Tintin: Permata Castafiore
 Permata Castafiore sangat berbeda dari kisah-kisah petualangan Tintin yang lain. Di buku ini, Tintin memecahkan misteri yang terjadi di kediamannya sendiri. Dari awal sampai akhir kisah ini, kita tidak beranjak dari Puri Moulinsart. Hergé memang mengatakan ingin menyederhanakan kisah Tintin, maka ia pun menulis kisah yang bagai novel detektif karya Agatha Christie.
Permata Castafiore sangat berbeda dari kisah-kisah petualangan Tintin yang lain. Di buku ini, Tintin memecahkan misteri yang terjadi di kediamannya sendiri. Dari awal sampai akhir kisah ini, kita tidak beranjak dari Puri Moulinsart. Hergé memang mengatakan ingin menyederhanakan kisah Tintin, maka ia pun menulis kisah yang bagai novel detektif karya Agatha Christie.Selain itu, dalam buku ini Hergé juga sebetulnya mengungkapkan banyak hal yang betul-betul terjadi dalam kehidupannya sendiri. Misalnya keinginannya untuk beristirahat di rumah, seperti yang diutarakan Kapten Haddock. Tuan Bolt (Boullu, dalam edisi Prancis) si tukang bangunan sebetulnya juga ada di kehidupan nyata, dan seperti di buku ini, orang itu juga sama susahnya dipanggil.
Kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Tristan Bior, perancang favorit Bianca Castafiore, sebetulnya adalah plesetan dari Christian Dior, perancang busana terkenal dari Prancis. Dan Bianca Castafiore sendiri jelas menggambarkan Maria Callas, penyanyi opera terkenal.
Untuk para pembaca yang teliti, Hergé memberi petunjuk tentang salah satu buku favoritnya. Di halaman 43, tampak Tintin sedang membaca buku Treasure Island karangan R.L. Stevenson, yang bersama Robinson Crusoe (Defoe) dan The Three Musketeers termasuk dalam sepuluh buku yang paling disukainya.
Karena bersimpati pada kaum gipsi, Hergé tadinya ingin lebih fokus pada kelompok minoritas ini. Dalam beberapa dialog di buku ini, kita bisa melihat bagaimana perasaan Hergé terhadap mereka. Misalnya Kapten Haddock, yang mengizinkan para gipsi berkemah di halaman Puri Moulinsart, juga Tintin yang membela mereka di hadapan Dupondt. Hergé menuangkan keahliannya menggambar pada panel yang menunjukkan rombongan gipsi sedang berkumpul di depan api unggun sambil bermain musik. Settingnya, diterangi sinar bulan purnama dan cahaya api unggun, sangatlah indah.
Kalau dalam Tintin di Tibet kita hanya sedikit melihat Profesor Lakmus, di Permata Castafiore ini kita bisa melihat bagaimana si profesor jenius itu menampilkan temuan terbarunya: televisi berwarna, benda yang ketika kisah ini pertama kali diterbitkan, sama sekali belum dikenal publik. Kita juga melihat bagaimana Lakmus jatuh cinta pada Bianca Castafiore, sampai mengabadikan nama penyanyi itu menjadi nama mawar ciptaannya.
Biarpun Permata Castafiore menarik dari segi cerita, ternyata buku ini kurang populer. Sepertinya para pembaca lebih suka "ramuan" kisah petualangan Tintin yang biasa, yaitu petualangan ke berbagai tempat dan adanya para "bandit". Karena itulah, Hergé kembali ke ramuan lama ini di dua kisah petualangan Tintin selanjutnya: Penerbangan 714 ke Sydney dan Tintin dan Picaros.
Sumber: Tintin The Complete Companion (Michael Farr)
(disebarkan oleh Dini)
Posted by editor at 12:52 AM 0 comments
Friday, November 7, 2008
Petualangan Tintin: LAUT MERAH
 Petualangan Tintin: Laut Merah aslinya berjudul Coke en Stock. Buku yang pertama kali terbit tahun 1958 ini bisa dibilang merupakan ajang reuni banyak "bandit" serial Tintin. Ada Jenderal Alcazar (Si Kuping Belah), Emir Ben Kalish Ezab dan Abdallah (Tintin di Negeri Emas Hitam), Rastapopoulos dan Oliveira da Figueira (Cerutu sang Firaun), Allan (Kepiting Bercapit Emas), Dr. J.W. Müller (Pulau Hitam), bahkan Dawson (Lotus Biru).
Petualangan Tintin: Laut Merah aslinya berjudul Coke en Stock. Buku yang pertama kali terbit tahun 1958 ini bisa dibilang merupakan ajang reuni banyak "bandit" serial Tintin. Ada Jenderal Alcazar (Si Kuping Belah), Emir Ben Kalish Ezab dan Abdallah (Tintin di Negeri Emas Hitam), Rastapopoulos dan Oliveira da Figueira (Cerutu sang Firaun), Allan (Kepiting Bercapit Emas), Dr. J.W. Müller (Pulau Hitam), bahkan Dawson (Lotus Biru).
Sejak awal kita sudah diajak terlibat dalam berbagai petualangan seru, dari perdagangan senjata, kudeta di Timur Tengah, sampai perdagangan budak. Inilah yang mendasari judul bahasa Prancis-nya, yang dalam pesan bersandi kisah ini diterjemahkan menjadi batu bara di kapal. Istilah ini mengacu ke orang-orang Afrika yang akan naik haji lewat laut tapi sebetulnya akan diperjualbelikan sebagai budak.
Hergé mengangkat topik perbudakan ini untuk membuktikan ia tidaklah rasis seperti yang dituduhkan orang karena Tintin di Congo. Namun niat baiknya berubah jadi bumerang. Empat tahun setelah buku Laut Merah terbit, ada artikel di Jeune Afrique yang menuduhnya rasis karena ia menggambarkan orang-orang Afrika di kisah ini menggunakan bahasa pidgin. Akhirnya Hergé merevisinya pada tahun 1967, memperbaiki tata bahasa orang-orang Afrika itu dan menggunakan cara Amerika yang mengurangi huruf dalam kata-kata, sehingga missié yang diprotes pun menjadi M'sieur.
Keseriusan Hergé menggarap karya-karyanya memang tidak usah diragukan lagi. Agar gambar kapal Ramona betul-betul akurat, ia dan Bob De Moor pulang-pergi dari Antwerp ke Gothenburg naik kapal. Penyelam yang akan memasang bom di kapal yang ditumpangi Tintin, Haddock, Milo, dan Szut juga dibuat berdasarkan foto penyelam Angkatan Laut Inggris yang bernama Lionel Crabb. Pria ini tidak pernah kembali dari misinya memeriksa lambung kapal Sovyet yang sedang berkunjung ke Inggris dan beberapa waktu kemudian tubuhnya yang sudah tak berkepala ditemukan terdampar di pantai.
Hal lain yang bisa kita lihat dalam buku ini adalah tingginya minat Hergé terhadap seni lukis. Di halaman 10 kita bisa melihat lukisan Le Canal du Loing karya Alfred Sisley, di halaman 36 ada lukisan Picasso, dan di halaman 51 tampak secuil lukisan Miro. Bahkan Senhor Oliveira da Figueira pun memasang lukisan dengan pigura indah yang tergantung miring di dinding rumahnya.
Akhirnya, di panel terakhir buku ini, kita bisa melihat Hergé sendiri. Dia muncul sebagai pria berjas hujan panjang di tengah jalan. Sedangkan Edgar-Pierre Jacobs tampak sebagai lelaki berdasi kupu-kupu dan berkacamata yang sedang mendengarkan musik dari radio.
Sumber: Tintin The Complete Companion (Michael Farr)
(Disebarkan oleh Dini. November 2008)
Posted by editor at 12:40 AM 0 comments
Tuesday, November 4, 2008
Penyelamat Kakakku (My Sister's Keeper) - Jodi Picoult
 Aku berkenalan dengan My Sister's Keeper lewat temanku yang meneteskan air mata di kantor ketika mendapat tugas membaca proof buku ini. Karena penasaran akhirnya aku memutuskan membaca buku itu sendiri. Tidak lama setelah mulai membaca buku itu mataku berkaca-kaca dan, akhirnya, ikut meneteskan air mata dan menghabiskan berlembar-lembar tisu.
Aku berkenalan dengan My Sister's Keeper lewat temanku yang meneteskan air mata di kantor ketika mendapat tugas membaca proof buku ini. Karena penasaran akhirnya aku memutuskan membaca buku itu sendiri. Tidak lama setelah mulai membaca buku itu mataku berkaca-kaca dan, akhirnya, ikut meneteskan air mata dan menghabiskan berlembar-lembar tisu.
Buku ini sendiri berkisah tentang keluarga beranggotakan lima orang. Keluarga yang mungkin hanya akan menjadi keluarga "biasa" jika putri tertua keluarga itu tidak mengidap leukemia. Sebagian besar cerita tentang keluarga dengan anggota keluarga yang mengidap penyakit mematikan berfokus pada si penderita. Tapi tidak demikian dengan buku ini. Fokus cerita buku ini bukanlah Kate, si penderita leukemia, melainkan Anna, adik Kate.
Siapa sebenarnya Anna? Anna adalah anak yang lahir melalui prosedur bayi tabung. Anak yang dirancang secara genetik agar bisa menjadi penyelamat hidup kakaknya.
Kate baru berusia dua tahun ketika didiagnosis menderita APL---leukemia promielostik akut--- penyakit leukemia langka. Kate hanya punya satu harapan untuk selamat: donor allergenic---saudara yang sama sempurna. Dan ketika Brian, kakak Kate, ternyata tidak bisa menjadi donor,
orangtua Kate, Sara dan Brian, akhirnya memutuskan untuk memiliki anak lagi. Bukan sembarang anak, tapi anak yang diprogram agar bisa memiliki kecocokan sempurna dengan Kate.
Beberapa saat setelah kelahirannya, Anna sudah harus menyumbangkan darah dari tali pusatnya. Beberapa tahun kemudian dia tanpa henti menjadi donor leukosit, sel induk, atau umsum tulang setiap kali Kate membutuhkan. Meskipun tubuhnya sehat, Anna harus menjalani puluhan suntikan, transfusi darah, dan operasi. Setiap kali Kate di rumah sakit, Anna pasti akan ada di sana untuk menyediakan apa pun yang saat itu dibutuhkan Kate.
Sampai suatu ketika, pada usianya yang ketiga belas, Anna mulai mempertanyakan siapa dirinya dan tujuan hidupnya. Puncaknya, ketika diminta menyerahkan ginjalnya kepada sang kakak, Anna akhirnya menggugat orangtuanya untuk memperoleh hak atas tubuhnya sendiri.
Aku punya dua orang adik. Jika aku diminta mendonorkan sesuatu untuk adikku aku akan melakukannya tanpa pikir panjang. Aku yakin hampir semua orang akan melakukannya tanpa ragu. Lalu kenapa Anna merasa keberatan melakukannya? Apakah Anna sebegitu kejam hingga tega menjatuhkan vonis hukuman mati bagi kakaknya dengan menolak menjadi donor kakaknya lagi?
Anna sebenarnya bukanlah sedang mencari perhatian seperti yang dituduhkan ibunya. Dia sedang berteriak meminta bantuan karena tidak bisa mengenali siapa dirinya. Selamanya dia merasa hanya sebagai penolong Kate. Dia tidak merasa dirinya sebagai pribadi utuh. Dia selalu menjadi bagian Kate. Gadis yang merasa diinginkan hanya untuk menjadi alat yang bisa digunakan untuk menolong kakaknya. Anak yang merasa tak kasatmata hingga orangtuanya membutuhkan darah atau bagian tubuhnya yang lain untuk Kate. Gadis yang untuk sekali dalam hidupnya ingin diberi kesempatan untuk memilih. Semua itu akhirnya menjadi bagian alasan Anna meminta pengacara untuk mewakilinya mengajukan petisi hak atas kebebasan medis.
Sara, sang ibu, merasa ia tanpa ragu akan dengan sukarela menjadi donor untuk Kate. Ia menganggap Anna akan merasakan hal yang sama sehingga tidak pernah mempertanyakan kesediaan Anna untuk menjadi donor bagi Kate.
Biasanya pada prosedur-prosedur medis, dan pada banyak hal lain, orangtua diizinkan membuat keputusan bagi anak karena mereka dianggap melakukannya demi kepentingan si anak. Tapi bagaimana jika mereka dibutakan oleh kepentingan anak yang lain?
Bagaimana jika karena ingin menyelamatkan salah satu anaknya, anak yang lain menjadi korban? Bahkan meski tidak ada yang dikorbankan oleh keputusan itu, apa jaminan bahwa keputusan orangtua untuk anak merupakan keputusan yang terbaik? Hal inilah menurutku yang paling menarik dari buku ini. Betapa sebenarnya kita tak selalu bisa membedakan antara hitam dan putih dengan mudah. Atau juga antara benar dan salah. Bahkan ketika kita tahu itu tindakan yang benar, belum tentu itu tindakan yang baik. Ya, berusaha sekeras mungkin untuk menyelamatkan anak kita adalah tindakan yang benar, tapi apakah mengorbankan anak yang satunya lagi merupakan hal yang baik?
Selain ceritanya yang menurutku kompleks, gaya penceritaan buku ini juga unik. Buku ini diceritakan melalui sudut pandang tujuh orang. Jadi selain menceritakan Anna, buku ini juga menceritakan konflik yang dialami anggota keluarga Fitzgerald yang lain, juga pengacara dan wali ad litem Anna.
Buku ini sendiri sekarang sudah diangkat ke layar lebar. Aku tidak sabar untuk melihat akting Cameron Diaz yang akan memerankan Sara dalam film ini. Buat yang mau nonton juga, aku menyarankan untuk membaca bukunya dulu sebelum nonton. Buat yang udah nonton dan merasa filmnya kurang bagus, ingat: Don't judge a book by it's movie.
(Disebarkan oleh Dian. November 2008)
Posted by editor at 9:05 PM 1 comments
Labels: Ulasan
Kehidupan di Pintu Kulkas - Alice Kuipers
Ada banyak cara menulis kisah cinta. Salah satunya dengan pesan-pesan singkat yang ditempelkan di pintu kulkas. Singkat, padat, nyaris tak menyentuh kata-kata puitis dan indah yang biasanya menjadi salah satu instrumen setia dalam kisah cinta yang mengharu biru. Bahkan ada kalanya pesan itu hanya berupa daftar barang belanjaan yang mesti dibeli: susu, apel, wortel untuk Peter si kelinci, jus (kau boleh pilih rasa apa). Atau mungkin teriakan supaya si ibu tidak lupa meninggalkan uang saku. Dan yang lebih singkat lagi: “Mom, aku dapat A!”
Tapi toh kita bisa temukan juga jejak-jejak cinta di antara singkat dan bergegasnya kehidupan yang dikisahkan di pintu kulkas itu. Dan betapa dalam... Dan meski tak satu kata puitis pun ditemukan di sana, kau ingin tahu hasilnya? Cucuran air mata dan hati yang diremas-remas, yang mengartikan cinta itu ada, dan akan tetap ada lama setelah kehidupan di pintu kulkas itu berakhir.
Oh ya, satu lagi yang membuat buku ini istimewa, setidaknya untuk saya: buku ini mengingatkan betapa banyak yang dapat dikatakan dalam begitu sedikit kata-kata, asalkan kita bersedia menyediakan waktu untuk mengatakannya.
(Disebarkan oleh Rosi. November 2008)
Posted by editor at 5:29 PM 0 comments
Sunday, October 26, 2008
Secuil Cerita Tentang Twilight Saga
Nggak seperti kebanyakan orang, buku pertama dalam Twilight Saga yang aku baca justru buku kedua. Ngebacanya juga tidak dengan sengaja, tapi karena Mbak Rosi ngasih tugas untuk bacaproof New Moon. Meskipun awalnya rada keder karena itu buku tebal banget, akhirnya aku malah nggak bisa berhenti baca, pengin cepet-cepet sampe ke halaman paling akhir. Jadi, akhirnya gue malah harus berterima kasih karena dikasih tugas yang sangat menyenangkan ;-)
Banyak orang bilang anak-anak muda zaman sekarang, terutama remajanya, nggak suka baca buku. Kalian setuju? Nggak dong, ya? Fenomena yang akhir-akhir ini terjadi, buku-buku remaja juga berhasil mencapai angka penjualan fantastis. Salah satu contohnya ya Twilight Saga ini.
Semuanya dimulai bulan Oktober 2005 ketika Little, Brown and Co. di Amrik sana menerbitkan novel pertama karya Stephenie Meyer yang berjudul Twilight. Dan cuma dalam waktu satu bulan, Twilight berhasil masuk dalam daftar New York Times Best Seller List untuk kategori young adult.
Selain dari New York Times, buku ini juga dilabeli Amazon.com sebagai “Best Book of the Decade… So Far”. Kira-kira dua bulan lalu, waktu aku browsing ke situs Amazon, sudah ada 1.675 orang yang menulis review buku ini, dan 1.331 di antaranya ngasih rating 5 bintang. Menariknya, orang-orang yang membuat review atau ngomongin buku ini di berbagai forum nggak cuma remaja, tapi ada ibu-ibu, bahkan nenek-nenek. Lumayan, dong? Maksudnya lumayan bikin penasaran, terutama buat kalian yang belum baca...
Saking cintanya sama buku ini, para fans menyebut diri mereka sebagai Twilighters. Bahkan penduduk kota Forks, kota yang sungguhan ada di negara bagian Washington, bikin hari khusus buat Stephenie Meyer. Sekarang ini, film layar lebar Twilight juga sedang dalam tahap akhir produksi. Menurut gosip-gosip yang beredar di internet filmnya bakal rilis bulan November/Desember 2008.
Karena kena virus New Moon, aku coba meng-google frasa “Twilight, Stephenie Meyer”, dan menghasilkan jutaan entri, mulai dari situs resmiTwilight, forum-forum diskusi, sampai puluhan YouTube personal yang menyediakan trailer film Twilight. Bahkan MTV juga menyediakan trailer ini di halaman depan situsnya.
Dan ternyata, Twilight nggak cuma disukai publik remaja di Amerika. Sekarang, Twilight sudah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa, termasuk Indonesia. Waktu aku coba browsing ke forum-forum diskusi dan blog orang Indonesia, udah ada buzz yang cukup seru tentang Twilight Saga di kalangan netters Indonesia.
Gimana sih cerita novel ini?
Dengan buzz sebesar itu, kalian pasti nanya, emang gimana sih ceritanya? Kalo kalian mau tahu ringkasan cerita lengkapnya, mendingan klik artikel yang dibuat Mbak Michelle deh.
Buat gue, di balik kisah cinta Bella-Edward yang pastinya bikin banyak cewek terpesona (not me! I vote for Jacob!=)), Stephenie Meyer menceritakan hal yang universal banget, yang dialami hampir tiap remaja meski dengan tingkat beda-beda. Tiap orang pasti pernah melalui masa-masa ketika mereka merasa bingung, pengin banget mencari jalan sendiri, tapi juga sekaligus berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. Atau ketika mereka jadi makin dewasa dan harus belajar bahwa tiap pilihan pasti punya konsekuensi, seperti Bella yang harus mikir seberapa banyak dia rela berkorban untuk bisa bareng terus sama Edward. Atau mungkin seberapa rela dia ngelepas Edward buat mendapatkan hal-hal lain? (Ha... ha... ha... I wish!)
Selain ceritanya, aku pikir pasti menarik juga untuk mikirin judul yang dipakai Meyer buat keempat bukunya. Dimulai dari Twilight, kata yang kira-kira menggambarkan senja ketika matahari udah terbenam dan suasana mulai gelap. Terus dilanjutkan dengan New Moon, suasana malam ketika lagi ada bulan baru. Masih inget dong pelajaran SD bahwa waktu bulan baru tuh bagian bulan yang keliatan dari bumi baru sedikit? Dilanjutkan sama Eclipse (gerhana) ketika betul-betul nggak ada cahaya di langit. Dan saga ini diakhiri dengan buku berjudul Breaking Dawn, saat-saat ketika fajar mulai menyingsing. Jadi pertanyaannya, di pikiran gue nih, pencerahan seperti apa yang bakal didapat Bella di akhir cerita, ya?
Dan pemikiran ini membuat gue nggak sabar nunggu-nunggu Breaking Dawn. Soalnya, kalau cuma berhenti di Eclipse, berarti aku akan tetap berada di kegelapan...:p Bagaimana konflik utama nantinya akan diselesaikan dan pencerahan seperti apa yang bakal didapat Bella memang tergantung sepenuhnya pada Meyer. Makanya, see you all in Breaking Dawn!
(Disebarkan oleh Nina. Oktober 2008)
Posted by editor at 6:21 PM 1 comments
Wednesday, October 22, 2008
Tintin di Tibet

Buku berjudul asli Tintin au Tibet ini terbit pada tahun 1960, merupakan buku ke-20 dalam serial Petualangan Tintin. Kisahnya tentang usaha Tintin menemukan teman lamanya Zhang yang menjadi korban akibat pesawatnya jatuh di Tibet.
Ketika menulis kisah ini, Hergé sedang menghadapi berbagai masalah. Pernikahannya yang sudah berusia dua puluh enam tahun dengan Germaine Kieckens goyah. Ia juga terus-menerus dituntut untuk memproduksi Tintin. Karena itulah ia diganggu mimpi buruk yang sering berisi hal-hal serbaputih.
Inilah yang kemudian muncul dalam Tintin di Tibet: hamparan salju di Himalaya. Kisah ini juga memuat keyakinan Hergé tentang persahabatan, baik antara Tintin dan Zhang, Haddock dan Tintin atau, yang paling menyentuh, antara yeti dan Zhang.
Tintin di Tibet bisa dibilang semacam terapi penyembuhan bagi Hergé, karena ketika ia selesai membuatnya, mimpi-mimpinya yang serbaputih pun menghilang. Ia juga telah bercerai dari Germaine dan memulai hidup baru bersama Fanny Vlaminck, seniman muda yang bekerja di studio Hergé. Hebatnya efek kisah petualangan di Tibet ini membuat Hergé menganggap kisah Tintin ini sebagai favoritnya.
Tadinya Hergé berniat menulis tentang Indian lagi, karena merasa masih banyak yang perlu ditulis tentang suku Indian, meski ia cukup berhasil mengungkapkan banyak eksploitasi yang dialami suku itu dalam Tintin di Amerika. Namun ia lantas memutuskan menulis tentang tempat yang sama sekali baru tapi tetap berhubungan dengan masa lalunya, yaitu teman lamanya: Chang, pematung muda dari China yang belajar di Belgia. Hergé kehilangan kontak dengannya karena kekacauan akibat invasi China ke Jepang, Perang Dunia, dan revolusi komunis. Baru pada tahun 1975 ia berhasil melacak Chang, yang pada tahun 1981 kembali ke Brussels dan akhirnya menetap di Paris.
Dalam kisah yang sangat personal bagi Hergé ini, ia juga menghadirkan dua hal yang diminatinya: indra keenam dan mistik dalam Buddhisme Tibet. Seperti yang kita ketahui, Tintin bermimpi tentang Zhang yang terluka di tengah salju dan meminta pertolongannya. Karena mimpi inilah Tintin berangkat ke Nepal biarpun semua orang bersikap skeptis karena tipis sekali harapan ada korban pesawat jatuh itu yang masih hidup.
Masalah indra keenam ini lantas menyatu dengan mistik ketika salah satu pendeta Buddha di Tibet yang bernama Kilat Terang tahu-tahu melayang dan melihat visi tentang Tintin dan teman-temannya yang dalam bahaya besar karena terkubur salju longsor.
Sedangkan tentang yeti, Hergé bisa dibilang menampilkan fenomena yang melanda masyarakat pada akhir tahun 1950an. Koran-koran dipenuhi laporan tentang munculnya yeti, jejak kaki misterius (seperti yang tampak di cover buku ini), dan berbagai penjelasannya. Hergé menggambarkan yeti sebagai makhluk yang memiliki banyak sifat manusiawi. Yeti merawat Zhang yang terluka dan menyayangi anak itu sehingga ia melolong sedih ketika Zhang dan rombongannya meninggalkan Tibet.
Salah satu hal yang paling mengagumkan dalam buku ini adalah keakuratan Hergé dalam menggambarkan banyak hal di dalamnya. Ini tidaklah mengherankan, karena Hergé menggunakan banyak referensi, misalnya buku-buku karya Alexandra David-Neel, ahli tentang Tibet. Kemah yang didirikan sherpa Tharkey, deskripsi tentang tsampa (makanan Tibet), tugu chorten, chang (bir sangat keras khas Tibet), juga tradisi penyambutan tamu kehormatan berupa pemberian syal sutra, semua itu dibuat Hergé berdasarkan buku-buku David-Neel.
Referensi Hergé yang lain adalah majalah National Geographic. Banyak lanskap dalam panel Tintin di Tibet yang dibuatnya berdasarkan foto-foto di majalah itu. Misalnya gua salju tempat Zhang berlindung dan prosesi para lama, lengkap dengan atribut dan alat musik mereka. Kehebatan Hergé soal lanskap bisa kita lihat pada tiga panel yang secara berurutan menggambarkan satu pemandangan pegunungan sehingga kita bisa membayangkan luasnya.
Akhirnya, Tintin di Tibet bukan hanya merupakan karya yang luar biasa karena latar belakang kehidupan pribadi Hergé ketika menulisnya, tapi juga karena menunjukkan keprihatinan Hergé tentang nasib negeri itu yang diekspansi China pada tahun 1950-an. Pada tahun 2001, Hergé Foundation mendesak penarikan edisi bahasa China buku ini, yang diterbitkan dengan judul Tintin in China's Tibet. Buku ini kemudian diterbitkan kembali dengan terjemahan judul yang benar. Pada 1 Juni 2006, Tintin menjadi tokoh fiktif pertama yang dianugrahi penghargaan Truth of Light oleh Dalai Lama. Edisi bahasa Tibet buku ini diterbitkan Casterman pada tahun 1994.
Sumber:
-Tintin The Complete Companion (Michael Farr)
-Wikipedia
(Disebarkan oleh Dini. Oktober 2008)
Posted by editor at 7:01 PM 1 comments
Laika, Anjing yang Terbang di Antara Bintang-Bintang
 Selain kucing dan kuda, anjing menjadi binatang yang paling banyak diabadikan dalam literatur. Tidak mengherankan, sebab sejak awal mula peradaban, anjing telah berinteraksi dengan manusia, sebagai binatang kesayangan, pekerja, pelindung, maupun bahan eksperimen. Dalam literatur, kita banyak menjumpai tokoh anjing, baik sebagai musuh ataupun sahabat. Dalam serial Lima Sekawan, ada Timmy yang sangat sayang pada George; Tintin mempunyai Snowy yang lucu dan cerdas; Nicholas Sparks mengisahkan tentang Singer, anjing Great Dane yang setia sampai mati pada majikannya dalam The Guardian; Kate DiCamillo menuturkan kisah mengharukan dalam Because of Winn-Dixie; juga ada Squirrel yang merindukan rumah yang hangat dalam A Dog’s Life karya Ann M. Martin.
Selain kucing dan kuda, anjing menjadi binatang yang paling banyak diabadikan dalam literatur. Tidak mengherankan, sebab sejak awal mula peradaban, anjing telah berinteraksi dengan manusia, sebagai binatang kesayangan, pekerja, pelindung, maupun bahan eksperimen. Dalam literatur, kita banyak menjumpai tokoh anjing, baik sebagai musuh ataupun sahabat. Dalam serial Lima Sekawan, ada Timmy yang sangat sayang pada George; Tintin mempunyai Snowy yang lucu dan cerdas; Nicholas Sparks mengisahkan tentang Singer, anjing Great Dane yang setia sampai mati pada majikannya dalam The Guardian; Kate DiCamillo menuturkan kisah mengharukan dalam Because of Winn-Dixie; juga ada Squirrel yang merindukan rumah yang hangat dalam A Dog’s Life karya Ann M. Martin.
Dan sekarang giliran Laika diabadikan dalam bentuk novel grafis.  Laika adalah anjing kecil telantar yang diambil dari jalanan di Moscow, untuk diikutsertakan sebagai binatang percobaan dalam program Sputnik 2, pada tanggal 3 November 1957.
Laika adalah anjing kecil telantar yang diambil dari jalanan di Moscow, untuk diikutsertakan sebagai binatang percobaan dalam program Sputnik 2, pada tanggal 3 November 1957.
Novel grafis ini dibuka dengan pemandangan padang salju di Rusia, dan seorang pria bernama Korolev. Delapa n belas tahun kemudian, dia menjadi Chief Designer Sputnik. Kesuksesan peluncuran Sputnik membuat Perdana Menteri Nikita Khrushchev menuntut peluncuran kendaraan orbital kedua. Tenggat waktu yang diberikan hanya satu bulan… dan kali ini harus membawa makhluk hidup di dalamnya. Pada masa itu, Amerika dan Rusia yang terlibat perang dingin, saling berlomba menjadi yang pertama dan paling unggul dalam proyek antariksa mereka. Sebelum mengirim manusia ke angkasa luar, binatanglah yang lebih dulu dikirim. Amerika menggunakan simpanse, sementara Rusia menggunakan anjing. Yang d
n belas tahun kemudian, dia menjadi Chief Designer Sputnik. Kesuksesan peluncuran Sputnik membuat Perdana Menteri Nikita Khrushchev menuntut peluncuran kendaraan orbital kedua. Tenggat waktu yang diberikan hanya satu bulan… dan kali ini harus membawa makhluk hidup di dalamnya. Pada masa itu, Amerika dan Rusia yang terlibat perang dingin, saling berlomba menjadi yang pertama dan paling unggul dalam proyek antariksa mereka. Sebelum mengirim manusia ke angkasa luar, binatanglah yang lebih dulu dikirim. Amerika menggunakan simpanse, sementara Rusia menggunakan anjing. Yang d ipilih anjing-anjing jalanan, dengan asumsi mereka sudah terbiasa menghadapi kondisi hidup yang berat, sehingga akan lebih tangguh ketika menjalani eksperimen-eksperimen. Laika terpilih karena di antara calon-calon lainnya, dialah yang paling manis sifatnya, dan paling sabar menjalani apa pun. Eksperimen ini mengukir jalan bagi pengiriman manusia ke angkasa luar. Nam
ipilih anjing-anjing jalanan, dengan asumsi mereka sudah terbiasa menghadapi kondisi hidup yang berat, sehingga akan lebih tangguh ketika menjalani eksperimen-eksperimen. Laika terpilih karena di antara calon-calon lainnya, dialah yang paling manis sifatnya, dan paling sabar menjalani apa pun. Eksperimen ini mengukir jalan bagi pengiriman manusia ke angkasa luar. Nam un kebenaran tentang peristiwa sesungguhnya yang terjadi atas Laika baru berpuluh tahun kemudian diungkapkan. Setelah keruntuhan rezim Soviet, pada tahun 1998, Oleg Gazenko, salah satu ilmuwan yang terlibat dalam eksperimen tersebut, menyatakan penyesalannya atas apa yang terjadi. Dan pada tanggal 11 April 2008, sebuah monumen untuk mengenang Laika diresmikan di Moscow.
un kebenaran tentang peristiwa sesungguhnya yang terjadi atas Laika baru berpuluh tahun kemudian diungkapkan. Setelah keruntuhan rezim Soviet, pada tahun 1998, Oleg Gazenko, salah satu ilmuwan yang terlibat dalam eksperimen tersebut, menyatakan penyesalannya atas apa yang terjadi. Dan pada tanggal 11 April 2008, sebuah monumen untuk mengenang Laika diresmikan di Moscow.
Laika bukan sekadar kisah tentang anjing. Berbagai unsur berbaur di dalamnya. Ada unsur politik, penelitian-penelitian ruang angkasa, interaksi antara manusia dengan hewan-hewan yang terlibat dalam program Sputnik 2, dan hal-hal yang dilakukan manusia atas nama ilmu pengetahuan dan kemajuan. Banyak pula momen inspiratif serta mengharukan untuk mengimbangi kisah tragis yang tak terelakkan ini. Nick Abadzis, penulis sekaligus ilustrator Laika, melakukan riset mendalam sebelum memulai proyek Laika. Nick khusus datang ke Moscow u ntuk mencari informasi tentang para insinyur, teknisi, dan dokter-dokter yang selama ini tidak ditonjolkan oleh rezim Soviet, dan terutama tentang Korolev, Chief Engineer yang merancang Sputnik 1 dan 2. Rumah Korolev di Rusia telah dijadikan museum dan dari sanalah Nick mengumpulkan kesan-kesan tentang kepribadian Korolev serta orang-orang yang bekerja bersamanya. Kunjungan ke Moscow itu juga digunakannya untuk mendapatkan rasa tentang negeri itu, budayanya, serta orang-orangnya.
ntuk mencari informasi tentang para insinyur, teknisi, dan dokter-dokter yang selama ini tidak ditonjolkan oleh rezim Soviet, dan terutama tentang Korolev, Chief Engineer yang merancang Sputnik 1 dan 2. Rumah Korolev di Rusia telah dijadikan museum dan dari sanalah Nick mengumpulkan kesan-kesan tentang kepribadian Korolev serta orang-orang yang bekerja bersamanya. Kunjungan ke Moscow itu juga digunakannya untuk mendapatkan rasa tentang negeri itu, budayanya, serta orang-orangnya.
Tidak perlu menjadi pencinta anjing untuk bisa merasa tersentuh dengan kisah ini. Laika adalah bacaan untuk setiap orang.
(disebarkan oleh Tanti, Oktober 2008)
Posted by Work and stuff at 10:54 AM 1 comments
Labels: Ulasan
Tuesday, October 21, 2008
Kitab Tentang yang Telah Hilang - John Connolly
 Entah bagaimana saya mulai bercerita tentang buku ini. The Book of Lost Things atau terjemahannya Kitab Tentang yang Telah Hilang adalah novel fantasi karya John Connolly yang dikenal sebagai pengarang novel kriminal. Jadi wajar saja jika buku ini diwarnai ketegangan-ketegangan ala novel thriller.
Entah bagaimana saya mulai bercerita tentang buku ini. The Book of Lost Things atau terjemahannya Kitab Tentang yang Telah Hilang adalah novel fantasi karya John Connolly yang dikenal sebagai pengarang novel kriminal. Jadi wajar saja jika buku ini diwarnai ketegangan-ketegangan ala novel thriller.Saya tidak bisa berhenti membaca buku yang sinting ini. Ceritanya mengalir dalam twist-twist yang membuat bulu kuduk berdiri. Emosi saya habis dipermainkan oleh isi cerita. Takut, cemas, bahkan sedih berputar-putar dalam hati saya. Yang pasti seusai membaca buku ini saya akan membaca novel John Connolly yang lain.
Buku ini dimulai ketika ibu David sakit keras. David---tokoh utama dalam buku ini---adalah anak lelaki berusia 12 tahun. Setting pada masa perang dunia kedua menambah kesuraman dan kepedihan yang dirasakan David. Ia melakukan segala yang bisa dilakukannya agar ibunya tidak meninggal, tapi siapalah yang bisa mencegah kematian?
Kesedihan David makin menjadi-jadi ketika ayahnya menikah lagi dengan Rose dan ia memiliki adik tiri. David juga harus pindah ke rumah keluarga Rose yang besar. Di rumah besar itu, David sering melihat penampakan sosok manusia bungkuk. David merasa makin tidak bahagia, sering bertengkar dengan ibu tirinya, dan membenci adik tirinya setengah mati. Ia kepingin ibunya tidak usah meninggal dan ia bisa hidup bahagia bersama ayah dan ibunya seperti dulu. Kecintaan David terhadap buku dan dongeng membuatnya melarikan diri dari kepedihan ke dalam buku-buku "warisan" Jonathan, paman Rose.
Suatu malam serangan bom dari pesawat terbang "mengantar" David masuk ke alam lain. Alam di mana dunia dongeng yang biasa dibacanya menjadi nyata. Namun negeri dongeng itu tidaklah polos dan indah seperti yang biasa dibacanya. Negeri dongeng yang dimasuki David adalah dunia yang sadis, menyeramkan, dan keji tak kenal ampun. Di sana Snow White, Putri Tidur, dan Tudung merah bukanlah seperti yang dibacanya dalam buku cerita. Di dunia macam itulah David tersesat dan tak bisa pulang.
Untuk bisa pulang ke dunia nyata, konon David harus bertemu dengan sang raja penguasa negeri yang memiliki kitab misterius: Kitab Tentang yang Telah Hilang. Akan tetapi perjalanan menemui sang raja penuh dengan bahaya. Makhluk jadi-jadian dan kawanan manusia serigala yang ingin mengudeta raja tua itu kini siap berperang dan menghabisi siapa pun yang menghalangi jalan mereka.
Di negeri itu David bertemu dan dibantu oleh tukang kayu baik hati dan Roland sang kesatria yang menyimpan banyak rahasia. Dan di negeri itu pula David berhadapan dengan lelaki bungkuk yang selama ini menguntitnya dan memiliki maksud jahat yang tak terbayangkan terhadapnya. David menghadapi pembunuhan, mutilasi, homoseksualitas, dan kanibalisme di negeri dongeng tersebut. Melalui segala petualangan yang dilewatinya, David yang masuk ke negeri ini sebagai anak lugu perlahan-lahan mencapai kedewasaan.
Walaupun bercerita tentang dongeng dan tokoh utamanya berusia 12 tahun, Kitab Tentang yang Telah Hilang bukanlah buku yang pantas untuk anak-anak atau pra-remaja. Kisah-kisah di negeri dongeng ini memiliki unsur sadisme dan seksual yang bejat. Ya, ibaratnya sehabis membaca novel ini, saya tidak bisa membayangkan cerita dongeng dengan cara yang sama lagi.
(Disebarkan oleh Hetih. Oktober 2008)
Posted by editor at 6:39 PM 1 comments
Labels: Ulasan
Thursday, October 16, 2008
Trilogi D'Angel - Luna Torashyngu
 Tak terasa dalam 3 tahun sejarah penerbitan karyanya di GPU, Luna sudah menerakan angka 9. Pukul rata itu berarti ada 3 buku per tahun. Sungguh produktif untuk ukuran penulis cerita remaja Indonesia.
Tak terasa dalam 3 tahun sejarah penerbitan karyanya di GPU, Luna sudah menerakan angka 9. Pukul rata itu berarti ada 3 buku per tahun. Sungguh produktif untuk ukuran penulis cerita remaja Indonesia.Tak heran, namanya pun mulai dikenal akrab di kalangan pecinta TeenLit Indonesia. Poling majalah GADIS bahkan memilihnya jadi salah satu dari tiga pengarang cerita remaja lokal yang paling ngetop (dua lainnya adalah Esti Kinasih dan Rachmania Arunita).
Menurut saya, Luna mengawali karier menulisnya dengan strategi yang baik---entah disengaja ataupun tidak---yaitu merebut pasar dengan cerita-cerita cinta yang ringan, agak dorama, lembut, dan sangat berselera pasar remaja. Begitu pasar sudah di tangan, Luna mulai mengeksplorasi ranah yang tidak awam bagi pasar remaja: science fiction.
Luna mulai menunjukkan kelasnya pada Beauty and the Best (2006) dan mengulangi lagi kepiawaiannya merangkai cerita pada Lovasket (2007). Kedua novel ini sangat mengalir, alurnya padat, logika ceritanya terjaga baik. Memang kekuatan utama novel-novel Luna ada pada logika cerita yang sangat masuk akal dan alur yang padat hingga membuat pembaca menolak meletakkan novelnya hingga tamat. Ini juga yang disajikannya pada trilogi D'Angel.
Trilogi ini membawa Luna ke ranah science fiction, tanpa meninggalkan naungannya pada genre TeenLit. Dengan tokoh Fika yang masih remaja kelas 1 SMA (pada buku pertama, D'Angel), Luna tetap bisa bebas menggunakan bahasa yang tidak kaku dan lincah, meskipun tema yang ditawarkan bisa saja jadi berat bila pemilihan tokohnya bukan remaja. Kesan lincah khas remaja ini juga tidak hilang meskipun tema lalu meluas kepada spionase, militer, konspirasi internasional, dan percobaan ilmiah. Luna juga tidak berpanjang-panjang memusingkan pembacanya dengan teori-teori sulit. Teori ilmiah sekadar memenuhi logika cerita, sehingga cerita tidak timpang, dan novelnya masih sangat bisa dinikmati tanpa mengerutkan dahi.

Alkisah Rafika Handayani adalah siswi unggulan di sekolahnya. Bintang lapangan voli, juga bintang kelas. Fisiknya pun cantik bening, hingga memikat salah satu kakak kelasnya dan akhirnya mereka pacaran. Tapi saat merayakan peristiwa jadian itu, Fika diculik. Mulailah thriller kejar-kejaran dari basement salah satu mal di Jakarta yang diwarnai adegan tembak-tembakan. Kenapa Fika diculik? Andika, cowok yang menolongnya memberitahu bahwa Fika sebenarnya bukan manusia. Dia bisa sangat sempurna secara fisik dan otak karena dia adalah Genoid hasil percobaan yang mencoba membuat manusia sempurna. Saat ini nyawanya terancam karena Jenderal Rastaji ingin membuat pasukan yang terdiri atas Genoid, dan membutuhkan Fika sebagai contoh. Kejar-mengejar makin seru, dan ditutup dengan hancurnya laboratorium Genoid di dekat Bogor. Fika yang kehidupannya hancur lari ke Malaysia.
Buku kedua, D'Angel: Rose, dibuka dengan ditemukannya Fika di Malaysia. Fika diminta pulang ke Indonesia (meskipun dia dituduh melakukan pembunuhan) untuk membantu polisi menemukan putri seorang koruptor. Fika kembali menjadi anak SMA. Meskipun tugasnya berat, Fika merasa kembali menemukan dunianya. Fika mendapatkan sahabat-sahabat baru, tapi di lain pihak musuh lamanya, Jenderal Rastaji muncul lagi, semakin kuat serta sadis. Jenderal Rastaji juga mengincar putri koruptor yang dicari Fika, demi mendapatkan dana yang tersimpan di salah satu bank di Swiss. Akhirnya jenderal keji ini menculik sahabat-sahabat baru Fika. Ia harus menggunakan kemampuan Genoid-nya dan berkelahi habis-habisan dengan Genoid lain untuk menyelamatkan teman-temannya. Tapi di penghujung cerita, Jenderal Rastaji terbunuh.
Layaknya kisah thriller bersambung, benarkah sang musuh besar sudah mati? Pada D'Angel: Princess, Fika diminta menjadi pengawal putri presiden, karena ada ancaman pembunuhan keluarga presiden. Sekali lagi Fika menyamar jadi anak SMA supaya bisa membayangi sang putri, Gya. Tapi Gya bukan pribadi yang menyenangkan. Merasa teman-teman hanya mendekatinya untuk mencari keuntungan, Gya memasang topeng judes dan dingin. Fika berusaha mencairkan kebekuan hati Gya sambil menjalankan tugasnya. Dan akhirnya Fika menghadapi konfrontasi final dengan musuh besarnya. Kali ini Fika harus melawan Genoid yang lebih kuat. Juga menata hatinya lagi karena Andika kembali muncul.

Dilirik dari sudut cerita, kisah trilogi D'Angel sangat berbeda dengan TeenLit pop yang merajai pasar. D'Angel yang full action ala film Hollywood ini benar-benar bisa jadi pilihan bacaan seru yang menghibur.
Rupanya kiprah Luna di ranah science fiction-action-TeenLit ini belum akan usai. Atau mungkin tepatnya, Luna justru "pulang ke rumah". Dan membawa warna baru bagi dunia TeenLit Indonesia.
(disebarkan oleh Donna, Oktober 2008)
Posted by editor at 7:06 PM 5 comments
Labels: Ulasan
Twilight

“I decided as long as I was going to hell, I might as well do it thoroughly.”
Perempuan mana yang nggak lumer kalo ada cowok ganteng, perkasa, berkulit pualam dan bermata keemasan, bicara seperti ini kepadanya?
Tak terkecuali Bella Swan. Seorang siswi sekolah menengah yang berpenampilan biasa-biasa saja.
Sejak pertama kali Bella melihat Edward Cullen di kantin sekolahnya yang baru di kota Forks, ia sudah sangat tertarik padanya. Ada sesuatu pada sosok Edward yang membuat dia—dan keluarganya—terlihat lebih menonjol dibanding orang lain. Sayangnya, sikap Edward ke Bella pada awal perkenalan mereka sungguh tidak menyenangkan. Entah kenapa, Edward terlihat benci dan jijik sekali sama Bella.
Suatu ketika, Bella dan teman-temannya yang baru piknik ke pantai. Di sana ia ketemu Jacob, anak yang berasal dan bersekolah di pemukiman Indian. Jacob menceritakan bahwa Edward dan keluarganya tidak di terima di daerah pemukiman tersebut, merujuk pada suatu perjanjian yang dibuat oleh nenek moyangnya Jacob. Diceritakan juga dongeng setempat, bahwa keluarga Cullen dipercaya oleh bangsa Indian daerah situ sebagai keluarga vampir. Karena itulah ditetapkan batas-batas daerah.
Penasaran dengan sikap Edward yang jahat padanya, dan cerita yang baru didengarnya dari Jacob, Bella melakukan riset di internet mengenai vampir. Ada beberapa ciri yang menunjukkan bahwa Edward memang vampir, walaupun banyak juga yang tidak cocok.
Bella yang mudah sekali mengalami kecelakaan, beberapa kali diselamatkan Edward. Termasuk menjadikan dirinya sebagai tameng antara Bella dan mobil yang melaju kencang dan slip di jalanan bersalju. Aneka peristiwa heroik itu yang akhirnya membuat Edward dan Bella dekat. Pada suatu kesempatan, dengan takut-takut Bella mengkonfrontasi Edward kesimpulan dia mengenai siapa Edward sebenarnya. Terbukalah kenyataan bahwa Edward dan keluarganya memang keluarga vampir. Dengan tegas Edward mengatakan kepada Bella, bahwa sebaiknya mereka tidak terlalu dekat, karena bisa membahayakan nyawanya, walaupun Edward dan anggota keluarga Cullen lainnya sudah memilih gaya hidup “vegetarian” alias tidak menghisap darah manusia. Mereka mengenyangkan diri dengan menghisap darah binatang. Kesukaan Edward adalah darah singa gunung.
Tapi apa dikata, Bella sudah terlanjur mencintai Edward.
Ada tiga hal yang kuyakini kebenarannya. Pertama, Edward adalah vampir. Kedua, ada sebagian dirinya—dan aku tak tahu seberapa kuat bagian itu—yang haus akan darahku. Dan ketiga, aku jatuh cinta padanya, tanpa syarat, selamanya. (Bella; halaman 209)
Konflik yang disebabkan karena cinta Bella-Edward pun bermunculan. Termasuk bagaimana menjembatani segala kekurangan Bella yang manusia biasa dengan semua kelebihan Edward karena ia vampir. Namun hal tersebut sama sekali tidak mengurangi kadar cinta mereka. Cinta yang begitu kuat sehingga kita yang membaca pun ikut terobsesi.
Tidak diperhitungkan juga oleh mereka, konflik yang datang dari kawanan vampir lain. Tidak semua vampir sebaik keluarga Cullen. James dan Victoria, misalnya, yang secara kebetulan bertemu Bella ketika ia sedang bersama dengan keluarga Cullen. Insting pemburu James sangat kuat, sehingga ia mengacuhkan penjelasan Edward bahwa Bella tidak boleh dimangsa. Timbulah pertentangan antara kedua kawanan itu, disertai dengan kejar-kejaran dan usaha penyelamatan Bella.
Apakah Edward berhasil menyelamatkan Bella? Apakah cinta mereka cukup kuat menghadapi perbedaan besar mereka?
(disebarkan oleh Michelle, Oktober 2008)
Posted by michelle at 12:24 AM 1 comments
Labels: Ulasan